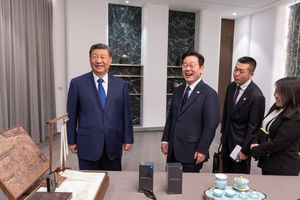ALARM perundungan (bullying) kembali meraung keras. Pada 15 Oktober 2025, kampus Universitas Udayana (Unud) di Bali diguncang kabar duka setelah Timothy Anugerah Saputra, mahasiswa semester VII Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), ditemukan meninggal dunia.
Ia diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai empat gedung FISIP setelah mengalami tekanan sosial yang berat dari lingkungan pergaulannya.
Kasus ini segera viral di media sosial karena kuatnya dugaan bahwa Timothy menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri.
Gen Z yang lahir di Bandung pada 25 Agustus 2003, sesungguhnya dikenal sebagai sosok yang ramah, santun, dan berprestasi.
Namun, di balik senyumnya, ternyata ia menyimpan luka yang dalam akibat ejekan bertubi-tubi yang berlangsung terus-menerus.
Tragedi ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tetapi juga peringatan keras akan pentingnya menciptakan lingkungan kampus (juga sekolah) yang aman, empatik, dan bebas dari kekerasan psikologis.
Peristiwa tragis ini mengguncang nalar publik bahwa bullying bukan hanya soal keisengan dan kenakalan remaja ataupun dinamika pergaulan, melainkan patologi sosial yang bisa merenggut nyawa, menghancurkan masa depan, dan meninggalkan luka psikologis yang tak pernah pulih, baik bagi korban maupun keluarganya.
Baca juga: Gen Z yang Terabaikan (Lagi) dari Panggung Kebijakan
Di tengah maraknya kampanye pendidikan karakter, literasi digital, dan penguatan kesehatan mental, tragedi ini seolah menampar wajah negara, seberapa serius kita sebenarnya dalam memahami, mencegah, dan menindak perundungan yang nyata-nyata sudah merupakan ancaman bagi generasi muda.
Seminar-seminar anti-bullying yang gencar digelar di sekolah dan kampus seakan tak pernah benar-benar menyentuh akar masalah.
Para pelaku perundungan toh masih merasa aman karena tahu bahwa konsekuensi terburuk hanyalah permintaan maaf yang dibacakan setelah segalanya terlambat.
Mirip yang dipertontonkan oleh para kriminal dan badut politik yang semakin sering jadi berita di layar gawai dan televisi.
Seolah semua selesai dengan sebaris penyesalan, tanpa pernah terlintas dalam benak mereka bahwa luka yang ditinggalkan pada korban akan menetap seumur hidup, membekas dalam bentuk trauma psikologis yang sulit disembuhkan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu berujung pada hilangnya nyawa.
Yang lebih menyedihkan, masyarakat kita masih sering gagal memahami dinamika psikologis yang dialami korban.
Alih-alih memberikan empati, tidak sedikit yang justru menyalahkan mereka, mengapa tidak melawan, mengapa tidak melapor, atau bahkan dalam kasus kekerasan seksual, menyalahkan pakaian korban.
Cara pandang seperti ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena memperparah rasa bersalah dan keterasingan yang dirasakan korban.
Dalam ilmu psikologi, respons terhadap tekanan ekstrem tidak selalu berbentuk perlawanan. Setidaknya ada tiga reaksi umum yang dikenal, freeze ketika tubuh dan pikiran membeku tidak mampu bereaksi, flight ketika korban memilih menghindar untuk menyelamatkan diri, dan fight ketika ia berusaha melawan.
Tiga respons ini bersifat alamiah dan berada di luar kendali kesadaran penuh. Artinya, tidak setiap korban memiliki kapasitas atau keberanian untuk melawan, dan kegagalannya bertahan bukanlah bukti kelemahan, melainkan refleksi dari tekanan psikologis yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian.
Di balik setiap tragedi perundungan yang berujung fatal, selalu ada satu pola berulang, negara hadir terlalu terlambat atau bahkan sama sekali tidak hadir.
Sekolah, sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar tentang nilai dan empati, sering kali justru menjadi ruang yang membiarkan kekerasan psikologis tumbuh subur.
Laporan korban kerap diabaikan, pelaku dilindungi atas nama baik institusi, dan penyelesaian kasus kerap berakhir dengan damai yang sejatinya tidak pernah menyembuhkan luka.
Aparat penegak hukum pun tidak jarang memandang enteng perundungan, kecuali jika sudah viral atau menelan korban jiwa.
Di balik semua ini, terdapat relasi kuasa yang timpang, pelaku kerap berasal dari keluarga pejabat, pengusaha, atau tokoh berpengaruh, sehingga kasusnya diredam demi reputasi.
Hasilnya, pesan yang tertanam di benak pelaku sangat jelas, mereka bisa lolos dari konsekuensi. Dan pesan itu pula yang membuat siklus perundungan terus berulang dari generasi ke generasi.
Baca juga: Gen Z dan Krisis Sunyi
Perdebatan tentang kriminalisasi bullying sesungguhnya hanya satu sisi dari persoalan yang jauh lebih kompleks.
Emma Jones dalam Should Bullying Be a Crime? (2020) menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut tidak semata-mata menyangkut bentuk sanksi yang pantas, melainkan juga bagaimana masyarakat mengakui beratnya konsekuensi sosial dan psikologis yang ditimbulkan.
Bullying bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan kekerasan psikososial yang dapat mengikis martabat, menghancurkan kepercayaan diri, dan bahkan merenggut nyawa.
Namun, sebagaimana diingatkan Jones, hukum pidana tidak selalu menjadi obat mujarab. Sanksi yang terlalu cepat dijatuhkan tanpa mekanisme pemulihan dapat menciptakan residivisme atau malah menutup peluang rehabilitasi.
Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang menuntut kombinasi antara ketegasan hukum bagi tindakan ekstrem dan strategi pencegahan serta pendidikan empati untuk kasus yang bersifat sosial dan struktural.
Di sinilah pemikiran Stoik yang ditawarkan Matthew Sharpe dalam Stoicism, Bullying, and Beyond: How to Keep Your Head When Others Around You Have Lost Theirs and Blame You (2022) memberikan kedalaman baru.
Jika hukum berperan menegakkan keadilan dari luar, maka Stoisisme menawarkan kekuatan dari dalam.