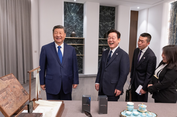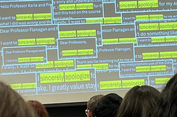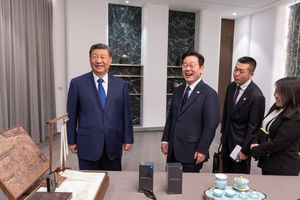Dari Narsissus Digital Menuju Digital Wellness (Bagian I)

"The most important thing about technology is how it changes people." - Jaron Lanier
RINA, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, awalnya hanya ingin mengecek Instagram sebentar pada pukul 9 malam sebelum menyelesaikan tugas kuliah. Namun, rencana 10 menit itu berubah menjadi maraton tiga jam scrolling tanpa henti.
Matanya mulai lelah, tugas kuliah belum tersentuh, malam kian larut, tapi jarinya tetap tak bisa berhenti menggeser layar.
"Besok aja deh tugasnya," pikirnya sambil terus scrolling video hingga dini hari.
Di waktu yang hampir bersamaan, pukul 2 dini hari, Andi (seorang karyawan swasta) masih menatap layar ponselnya dengan mata berat.
Ia berulang kali berkata, "Oke, bentar lagi", setiap kali hendak menutup aplikasi, padahal esok hari ia harus menghadiri rapat pagi di kantor.
Kisah Rina dan Andi bukanlah anomali, melainkan cerminan epidemi digital yang sedang melanda Indonesia.
Seperti Narcissus dalam mitologi Yunani yang terpaku pada bayangannya di permukaan air, jutaan netizen Indonesia kini terjebak dalam refleksi digital mereka sendiri.
Baca juga: Welcome GPT-5: Penciptanya Malah Bertanya, Apa yang Sudah Kita Lakukan?
Mereka scroll tanpa henti di media sosial, terpukau algoritma yang menampilkan versi ideal dari diri dan dunia mereka.
Survei Sharing Vision Indonesia pada Juni 2025, yang menggunakan kerangka Internet Addiction Test (IAT) oleh Kimberly Young terhadap lebih dari 5.000 responden mengungkapkan realitas yang mengkhawatirkan:
- 48 persen responden berulang kali berusaha mengurangi waktu online, namun gagal
- 48 persen sering kehilangan jam tidur demi internet
- 45 persen merasa hidup tanpa internet akan membosankan, tidak bermakna dan tidak menyenangkan
- 36 persen responden lebih sering menunggu waktu untuk online daripada menikmati kehidupan nyata
- 26 persen sering memilih tetap online daripada keluar dengan teman-teman
- 24 persen sering merahasiakan lamanya mereka online
- 23 persen sering merasakan tekanan dan kecemasan ketika offline, dan rasa itu hilang ketika online
- 22 persen terus memikirkan internet saat sedang offline
- 21 persen sering merasa kesal, menggerutu, atau membentak ketika ada yang mengganggu aktivitas onlinenya
Data ini menegaskan bahwa internet sudah melampaui fungsi dasarnya sebagai sarana, menjadi elemen yang menguasai ritme hidup sebagian masyarakat.
Fenomena statistik ini semakin terasa serius ketika kita menengok kasus-kasus ekstrem di lapangan.
Salah satunya terjadi di Jember, belum lama ini, di mana dua remaja kakak beradik mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan game online dan TikTok.
Sang adik, berusia 17 tahun, hampir seharian penuh menghabiskan waktunya bermain game. Sedangkan kakaknya yang berusia 19 tahun kehilangan orientasi waktu akibat penggunaan TikTok yang berlebihan.
Peristiwa ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan ujung dari gunung es transformasi neurologis yang diam-diam berlangsung pada jutaan orang Indonesia akibat paparan berlebihan terhadap dunia digital.
Memahami mekanisme jerat digital
Tristan Harris, mantan desainer etis Google sekaligus pendiri Center for Humane Technology, mengungkapkan, platform digital menggunakan apa yang ia sebut sebagai arsitektur persuasif, yaitu seperangkat mekanisme yang sengaja dirancang memaksimalkan keterikatan pengguna.
Fitur-fitur seperti infinite scroll, variable reward schedules, dan social approval loops bukanlah kebetulan, melainkan hasil riset psikologi yang mendalam untuk membuat orang tetap terpaku pada layar.
Baca juga: AI di Industri Kreatif Indonesia: Seruling, Dasein, dan Pertaruhan Orisinalitas
Harris bahkan menyebut smartphone sebagai “mesin slot di saku kita”, di mana setiap notifikasi atau swipe adalah tarikan handle mesin slot yang bisa memberikan reward (likes, pesan, konten menarik) atau tidak.
Ketidakpastian reward inilah yang membuat otak kita terus mencari stimulasi berikutnya.