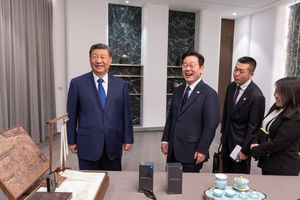Bolehkah AI Mencalonkan Diri dalam Pilpres 2029?

BOLEHKAH Artificial intelligence (AI) di Indonesia mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2029?
Pertanyaan ini terdengar naif. Namun, apa yang terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini tidak sesederhana kelihatannya.
Pada September 2025 lalu, Albania membuat gebrakan besar di dunia politik. Albania menjadi negara pertama di dunia yang mengangkat AI sebagai menteri di pemerintahan.
Perdana Menteri Edi Rama memperkenalkan AI bernama Diella, yang diberi tugas mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Diella memulai debutnya di parlemen pada 18 September 2025. Tujuannya sederhana, tapi ambisius: memberantas korupsi yang sudah lama membelit Albania.
Rama bahkan menyebut Diella sebagai “lompatan ke depan” untuk membawa negaranya selangkah lebih maju daripada negara-negara lain.
Berbeda dari manusia, Diella tidak bisa disuap atau terjebak nepotisme. Dibangun dengan teknologi AI generatif, ia mampu menganalisis data secara real-time, mendeteksi kejanggalan, dan memberikan rekomendasi dengan objektif.
Kehadiran Diella diharapkan bisa membuka jalan baru bagi pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Baca juga: Apakah Robotaxi Segera Menggantikan Manusia?
Kisah ini mencerminkan aspirasi masyarakat Albania yang lelah dengan korupsi yang menghambat pembangunan.
Di hadapan parlemen, Diella menegaskan bahwa dirinya “tidak datang untuk menggantikan orang”. Pesan ini seolah ingin menegaskan peran AI sebagai pendukung, bukan pengganti manusia.
Namun, langkah berani ini bukan tanpa perdebatan. Oposisi menilai pengangkatan Diella justru berbahaya dan tidak konstitusional.
Kekhawatiran terbesar mereka adalah hilangnya mekanisme akuntabilitas. Jika terjadi masalah dalam pengadaan publik, siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban? Bukanlah mesin, melainkan manusia yang seharusnya memegang mandat politik.
Terlepas dari kontroversi tersebut, kehadiran Diella tetap menginspirasi. Bagi sebagian kalangan, ini adalah bukti bahwa AI dapat menjadi alat pemberdayaan, terutama bagi negara berkembang yang ingin membangun tata kelola yang bersih dan efisien, di mana kepercayaan publik terhadap institusi pulih melalui teknologi netral.
Namun, dari perspektif kritis, langkah Albania bisa dibaca secara berbeda. Analisis ala Chomsky memandang langkah Albania sebagai bentuk "manufacturing consent" atau propaganda elite, di mana AI digunakan untuk menyembunyikan kekuasaan struktural.
Dalam pandangan analisis Chomsky, AI seperti ChatGPT sering kali hanyalah "false promise" yang tidak benar-benar cerdas.
Jika dilihat dari konteks ini, Diella bukanlah solusi netral, melainkan alat bagi Rama untuk mengonsolidasikan kontrol, yang mungkin saja dipengaruhi oleh korporasi teknologi Barat yang mendominasi data global.
Alih-alih mendorong kesetaraan, hal ini justru berpotensi memperburuk ketimpangan. Pasalnya, AI mengaburkan akuntabilitas manusiawi, mengingatkan pada kritik Chomsky terhadap bagaimana teknologi bisa dipakai untuk memperkuat hegemoni kekuasaan.
Selain Chomsky, analisis dari Daron Acemoglu juga memberi perspektif tajam. Menurut Acemoglu langkah ini sebagai potensi kosmetik.
Acemoglu memperingatkan bahwa AI yang masih "so-so" sering kali menggantikan manusia tanpa benar-benar meningkatkan nilai tambah.
Dalam kasus Albania, hal ini bisa menciptakan institusi ekstraktif—sesuai istilah Acemoglu—di mana elite politik seperti Rama memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan kekuasaan tanpa melakukan reformasi struktural.
Bukankah pada dasarnya AI tidak pernah bisa akurat 100 persen? Bahkan, sering kali akurasinya rendah, bias, atau halusinatif.
Bagaimana mungkin sistem yang rentan salah prediksi bisa dipakai untuk memberantas korupsi yang begitu kompleks?
Baca juga: Welcome GPT-5: Penciptanya Malah Bertanya, Apa yang Sudah Kita Lakukan?
Keraguan ini memperkuat pandangan bahwa kehadiran Diella mungkin lebih bersifat simbolis daripada benar-benar transformatif.
Selain Chomsky dan Acemoglu, perspektif filsafat teknologi juga memberi catatan penting.