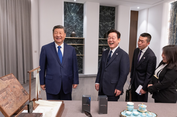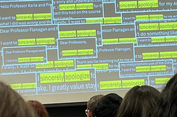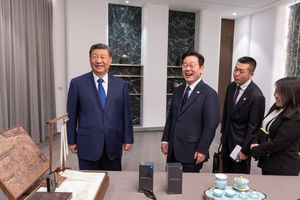Menjaga Akal Sehat di Era Data

KEHIDUPAN manusia modern tak lagi bisa dipisahkan dari data. Setiap klik, pencarian, dan percakapan di ruang digital meninggalkan jejak yang direkam, diolah, dan diperdagangkan. Dalam lanskap ini, pengguna internet sering kali hanya menjadi objek pengumpulan data tanpa kontrol publik yang memadai.
Data pribadi telah menjelma menjadi komoditas bernilai tinggi, yang diperebutkan oleh korporasi dan institusi negara. Di balik algoritma dan sistem kecerdasan buatan, informasi tentang perilaku, lokasi, dan preferensi pengguna dikemas menjadi profil yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi maupun politik.
Manuel Castells (2009) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “network society”—masyarakat yang kehidupannya dibentuk oleh aliran data dan logika jaringan. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi terpusat, melainkan tersebar melalui infrastruktur informasi yang tak kasatmata. Data pribadi bukan lagi milik individu, melainkan menjadi sumber daya strategis yang dieksploitasi oleh aktor-aktor ekonomi dan politik dalam skala global.
Christian Fuchs (2014) memperluas kritik ini dengan menyebut bahwa kapitalisme digital telah mengubah komunikasi menjadi komoditas. Platform media sosial dan teknologi informasi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk mengekstraksi nilai dari aktivitas pengguna. Dalam kerangka ini, komunikasi publik terancam direduksi menjadi transaksi ekonomi, bukan lagi ruang deliberasi yang sehat.
Baca juga: Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak
Tantangan Perlindungan Data
Indonesia telah memiliki payung hukum penting, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya” (Pasal 4) dan mewajibkan pengendali data untuk “memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan” (Pasal 20).
Ketentuan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan pengakuan bahwa data pribadi adalah bagian dari martabat manusia yang harus dijaga. Negara dan platform digital wajib memastikan data warga tidak disalahgunakan, tidak disimpan berlebihan, serta diproses berdasarkan dasar hukum yang jelas.
UU PDP juga memperkenalkan prinsip-prinsip seperti minimisasi data, tujuan yang sah dan spesifik, serta hak subjek data untuk mengakses dan memperbaiki informasi pribadinya (Pasal 6–9). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi warga untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi negara maupun penyedia layanan digital.
Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya literasi data di masyarakat, lemahnya mekanisme pengawasan, dan belum terbentuknya otoritas independen yang kuat membuat perlindungan data belum berjalan optimal.
Perlindungan data pribadi sejatinya tidak berhenti pada aspek hukum. Ia juga menyentuh ranah etika dan tanggung jawab komunikasi. Mengunggah, membagikan, atau memproses informasi pribadi bukan lagi tindakan netral, melainkan keputusan moral yang berdampak pada ruang publik digital secara luas.
Baca juga: Geopolitik dan Kedaulatan Data Digital Negara
Menata Ruang Komunikasi
Sosiolog Niklas Luhmann (1995) mengingatkan bahwa masyarakat modern hidup melalui komunikasi, dan kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang berlangsung di dalamnya. Artinya, memperkuat kebijakan komunikasi sama dengan memperkuat fondasi demokrasi sosial.
Dalam konteks era data, komunikasi tidak lagi sekadar pertukaran pesan antarmanusia, melainkan interaksi kompleks antara manusia dan sistem digital. Ketika komunikasi didorong oleh kepentingan ekonomi data, ruang publik kehilangan keseimbangannya. Percakapan publik yang seharusnya rasional dan inklusif berubah menjadi arus informasi yang bias dan manipulatif.
José van Dijck dan Thomas Poell (2013) menyebut bahwa platform digital kini berperan sebagai “gatekeepers” baru dalam komunikasi publik. Mereka tidak hanya memfasilitasi interaksi, tetapi juga mengatur algoritma, visibilitas, dan arah percakapan. Dalam logika platform, perhatian menjadi mata uang utama, dan komunikasi yang bernilai adalah yang paling viral—bukan yang paling bermakna.
Dalam konteks ini, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 hadir sebagai upaya negara untuk menata ulang ruang digital. SE ini mewajibkan instansi publik untuk mendaftarkan sistem elektroniknya, mengklasifikasikan informasi digital berdasarkan tingkat risiko, serta menerapkan moderasi konten dan pemutusan akses terhadap informasi yang melanggar hukum.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mulai mengambil peran aktif dalam menjaga integritas komunikasi publik dan mencegah eksploitasi data secara sewenang-wenang. Menjaga akal sehat di era data berarti mengembalikan komunikasi pada tujuannya: membangun pemahaman bersama, bukan memanen perhatian. Transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran informasi menjadi syarat agar komunikasi tetap manusiawi di tengah logika algoritma yang serbacepat.
Baca juga: Menkominfo Sebut Keamanan Data Digital Jadi Tanggung Jawab BSSN
Refleksi dan Tanggung Jawab Publik
Refleksi terhadap kebijakan komunikasi digital menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Kita perlu meninjau ulang keyakinan lama bahwa teknologi selalu membawa kemajuan, seolah-olah data bersifat netral. Faktanya, setiap teknologi membawa bias, dan setiap kebijakan komunikasi mencerminkan pilihan nilai.
Pemerintah perlu menyeimbangkan dua kepentingan: kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi. Di sisi lain, masyarakat ditantang untuk lebih kritis terhadap penggunaan datanya sendiri. Membaca terms and conditions, mengelola izin akses aplikasi, dan memahami risiko berbagi informasi pribadi adalah langkah kecil namun penting untuk memperkuat kontrol publik.
Lembaga negara maupun penyedia layanan digital juga harus memandang perlindungan data bukan sebagai beban administratif, melainkan tanggung jawab sosial. Kepercayaan publik dibangun dari transparansi, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi.
Baca juga: Tips Hindari Peretasan Siber, Serangan Ransomware, dan Melindungi Data Digital
Kewarasan Digital
Era digital menuntut kewarasan baru dalam berkomunikasi. Di tengah banjir informasi dan ilusi konektivitas, menjaga akal sehat berarti memelihara jarak kritis terhadap data dan teknologi. Castells (2009) mengingatkan bahwa ketika pengalaman manusia dijadikan bahan bakar ekonomi jaringan, yang terancam bukan hanya privasi, tetapi juga otonomi berpikir dan kebebasan berkehendak.
Karena itu, refleksi atas komunikasi publik menjadi penting untuk memastikan kebebasan informasi tidak berubah menjadi kekacauan informasi. Meninjau ulang asumsi, mengevaluasi praktik, dan mencari titik temu yang lebih manusiawi antara kebebasan dan keteraturan adalah langkah penting agar demokrasi tetap hidup.
Baca juga: 7 Fakta Transfer Data Pribadi Indonesia-AS, Bukan Penyerahan Bebas
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang