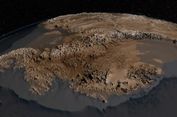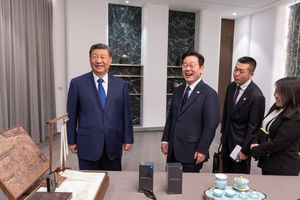Hari Hewan Sedunia: Teladan Santo Fransiskus dan Etika Lingkungan Kita

HARI Hewan Sedunia bukan sekadar momentum membagikan foto hewan kesayangan. Peringatan ini lahir dari semangat menghargai kehidupan dan kasih universal yang diwariskan Santo Fransiskus dari Asisi, seorang tokoh yang melampaui sekat agama dan budaya.
Fransiskus dikenal karena kesederhanaannya, keberaniannya menolak gaya hidup mewah, dan cintanya yang tulus kepada semua ciptaan, dari manusia hingga makhluk terkecil. Baginya, alam bukanlah objek untuk dieksploitasi, melainkan keluarga besar tempat manusia ikut menjadi bagian. Burung, serigala, hingga bunga di padang, semuanya ia panggil “saudara”.
Tanggal 4 Oktober dipilih sebagai Hari Hewan Sedunia untuk mengenang wafatnya Fransiskus. Dunia menjadikannya simbol universal bagi kasih terhadap hewan dan pengingat moral bahwa keseimbangan ekologi tidak bisa dipisahkan dari etika manusia.
Peringatan ini hanya akan menjadi rutinitas bila berhenti pada seremoni. Foto kucing dengan pita, anjing diarak di jalan, atau unggahan lucu di media sosial tentu menghangatkan hati, meski begitu, apa artinya jika hutan terus terkikis, sungai makin tercemar, dan satwa liar diburu tanpa henti?
Baca juga: Aktivitas Manusia Membuat Satwa Liar Mengecil, Hewan Ternak Membesar
Hari Hewan Sedunia menantang kita melampaui romantisme, menjadikannya momentum refleksi dan aksi nyata. Data ilmiah memberi peringatan keras yang tak bisa diabaikan.
Menurut Living Planet Report 2024 yang diterbitkan WWF dan Zoological Society of London, rata-rata populasi satwa liar vertebrata yang dipantau di seluruh dunia menurun 73 persen sejak 1970. Angka ini bukan total semua satwa, tetapi indeks rata-rata populasi yang dipantau. Penurunan paling tajam terjadi di Amerika Latin, tetapi tren serupa juga terlihat di Asia, termasuk Asia Tenggara.
Sementara itu, laporan IPBES Global Assessment 2019 memperkirakan sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan terancam punah dalam beberapa dekade mendatang, terutama akibat perubahan penggunaan lahan, eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, polusi, dan spesies invasif. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa krisis ekologi bukan ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini.
Indonesia, negeri megadiversitas dengan ribuan spesies unik, tidak kebal dari krisis ini. Kita sering berbangga dengan orangutan di Sumatra dan Kalimantan, komodo di Nusa Tenggara, cenderawasih di Papua, hingga terumbu karang Raja Ampat yang disebut jantung biodiversitas laut dunia. Di balik kebanggaan itu, ancaman nyata terus menghantui.
Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan aparat kepolisian masih rutin membongkar kasus perdagangan satwa liar. Pada 2025, Kementerian Kehutanan mengungkap jaringan perdagangan ilegal trenggiling lintas negara. Di Yogyakarta, Garda Animalia melaporkan lebih dari 34 ribu satwa diperjualbelikan lewat Facebook antara 2021–2023, termasuk 137 spesies dilindungi.
Kasus kukang, buaya muara, hingga elang Jawa kerap muncul sebagai bukti lemahnya pengawasan. Konflik antara manusia dan satwa juga makin sering terjadi. Gajah Sumatra yang kehilangan jalur jelajah karena hutan diubah jadi perkebunan dianggap hama, lalu diusir atau diburu. Harimau yang memangsa ternak dibalas dengan racun dan jerat. Padahal, konflik ini adalah cermin tata ruang yang gagal menjaga koridor satwa.
Infrastruktur dibangun tanpa memperhitungkan ekologi, sehingga satwa dipaksa masuk ke ruang manusia. Inilah wajah paradoks Indonesia: negeri dengan kekayaan hayati luar biasa, tetapi sering memperlakukannya sebagai beban, bukan anugerah.
Baca juga: Hari Gajah Sedunia, Ahli Ingatkan Pentingnya Koeksistensi dengan Satwa
 Anak gajah sumatera, Domang bersama induknya di kawasan TNTN di Kabupaten Pelalawan, Riau, beberapa waktu lalu.
Anak gajah sumatera, Domang bersama induknya di kawasan TNTN di Kabupaten Pelalawan, Riau, beberapa waktu lalu.Meski demikian, ada pula kisah harapan yang menunjukkan bahwa konservasi bukan utopia. Di Sorong, Papua Barat Daya, masyarakat adat Malaumkarta menjaga laut dengan kearifan lokal egeg—sistem larangan menangkap di zona tertentu untuk jangka waktu tertentu—sehingga ekosistem pulih dan hasil tangkapan justru lebih melimpah, bahkan sudah diakui dalam regulasi daerah.
Sementara itu, di ujung barat Jawa, Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon masih bertahan berkat pengawasan ketat dan keterlibatan warga sekitar. Dua kisah ini menegaskan bahwa baik melalui kearifan adat maupun kebijakan negara, kasih yang berpihak pada kehidupan bisa diwujudkan dalam capaian nyata.
Pertanyaannya: bagaimana menerjemahkan kasih Fransiskus dalam konteks sekarang? Jawabannya adalah mengubah empati menjadi tata kelola. Kasih yang hanya berhenti pada belas kasihan mudah menguap. Kasih yang diwujudkan dalam kebijakan akan bertahan lama.
Pemerintah daerah bisa menetapkan indikator sederhana: jumlah hektare koridor hijau yang dipulihkan, kasus perdagangan satwa yang benar-benar diproses hukum, persentase hewan jalanan yang divaksin dan disteril. Di tingkat pusat, kementerian bisa membuat papan kendali konservasi yang dipublikasikan secara berkala, agar publik dapat mengawasi.