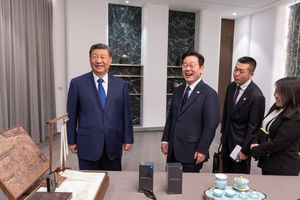Mengurai Jerat Kemiskinan dan Utang pada Masalah Kejiwaan

 Gejala depresi pada pria.
Gejala depresi pada pria.DI tengah deru pembangunan, Indonesia menyimpan sebuah epidemi yang tak bersuara, namun memakan korban dalam senyap: krisis kesehatan jiwa. Ini bukan lagi soal individu yang lemah, melainkan sebuah darurat kesehatan masyarakat.
Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa satu dari sepuluh orang Indonesia mengalami gangguan jiwa. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Angka ini menyiratkan bahwa di setiap keluarga dan lingkungan kerja, ada jiwa yang sedang berjuang dalam diam.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendefinisikan sehat bukan sekadar ketiadaan penyakit, melainkan “keadaan sejahtera yang utuh, baik secara fisik, mental, maupun sosial”. Namun, definisi ideal ini berbenturan dengan realitas pahit di lapangan, di mana jutaan jiwa terperangkap dalam tekanan yang sering kali berakar dari satu sumber yang sama: kesulitan ekonomi.
Menurut Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama gangguan mental di Indonesia, selain stigma dan lingkungan yang tidak mendukung. Krisis ini adalah epidemi sunyi yang menuntut kita untuk berhenti berbisik dan mulai berbicara dengan data, empati, dan solusi nyata.
Baca juga: Ramai soal Hotline Kesehatan Jiwa 119 Tidak Bisa Dihubungi, Kemenkes: Ada tapi Agak Lama
Lingkaran Setan: Dari Kantong Kosong ke Pikiran Kalut
Hubungan antara kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis bukanlah kebetulan, melainkan sebuah jalinan sebab-akibat yang terbukti secara ilmiah. Kemiskinan berfungsi sebagai "penguat risiko" (risk amplifier), menciptakan lingkungan beracun yang menggerogoti ketahanan mental secara perlahan namun pasti.
Stres finansial yang berkepanjangan terbukti dapat memicu depresi, gangguan kecemasan, bahkan menurunkan kemampuan kognitif. Studi oleh Anandi Mani, Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, dan Jiaying Zhao yang dipublikasikan dalam jurnal Science (2013) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi secara signifikan mengurangi kapasitas mental seseorang untuk mengambil keputusan rasional.
Efek ini bukan sekadar akibat stres, melainkan karena kemiskinan menyita ruang kognitif yang seharusnya digunakan untuk berpikir jernih dan strategis. Ini menciptakan lingkaran setan: kemiskinan memicu stres, stres mengganggu fungsi kognitif, dan fungsi kognitif yang terganggu melahirkan keputusan finansial buruk yang kian memperdalam jurang kemiskinan.
Skala masalah ini jauh lebih besar dari yang kita duga. Jika kita menggunakan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah-atas seperti Indonesia, hingga 60,3% penduduk kita dapat diklasifikasikan sebagai miskin atau rentan miskin. Ini berarti mayoritas bangsa ini hidup dengan tingkat stres keuangan yang signifikan, sebuah bom waktu kesehatan mental.
Di era digital, tekanan ini menemukan akselerator baru yang lebih kejam: pinjaman online (pinjol) ilegal. Berawal dari kebutuhan mendesak, banyak yang terjerat dalam bunga mencekik dan taktik penagihan yang tidak manusiawi. Kerusakan terbesarnya bersifat psikologis. Para penagih utang tidak hanya meneror korban, tetapi juga menyebarkan fitnah ke seluruh kontak telepon, mengeksploitasi rasa malu (gengsi) yang begitu mendalam dalam budaya kita.
Taktik "penghukuman sosial" ini adalah senjata pemusnah massal psikologis, yang terbukti mendorong korban ke jurang keputusasaan, depresi berat, bahkan bunuh diri, seperti yang tercatat dalam berbagai kasus, salah satunya menimpa seorang karyawan di Bekasi.
Baca juga: Kemenkes Bidik 50 Persen Puskesmas Layani Kesehatan Jiwa pada 2025
Angka yang Dibungkam: Bunuh Diri dan Ketimpangan Sistem
Tragedi puncak dari krisis ini adalah bunuh diri, sebuah fenomena yang skalanya di Indonesia ternyata jauh lebih mengerikan dari data resmi yang ada. Sebuah studi monumental yang dipublikasikan di jurnal medis bergengsi, The Lancet Regional Health - Southeast Asia, pada Februari 2024, mengungkap fakta yang mengejutkan: tingkat pelaporan yang kurang (underreporting) untuk kasus bunuh diri di Indonesia mencapai 859,10%. Artinya, untuk setiap satu kasus yang tercatat secara resmi, ada hampir sembilan kasus lain yang hilang tak terlacak.
Angka ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yang berarti kebijakan pencegahan kita selama ini "terbang buta", didasarkan pada data yang secara fundamental keliru. Penyebabnya kompleks, mulai dari stigma keluarga yang meminta penyebab kematian tidak dilaporkan secara akurat, hingga keyakinan budaya yang beragam.
Data dari studi yang sama juga menunjukkan kesenjangan yang tragis: tingkat bunuh diri di perdesaan 4,47 kali lebih tinggi daripada di perkotaan. Ironisnya, di sanalah kekosongan layanan paling parah terjadi. Sistem kesehatan kita timpang secara struktural.
Rasio psikiater di Indonesia adalah 1 berbanding 200.000 penduduk, sangat jauh dari standar WHO yaitu 1:30.000. Jumlah psikolog klinis pun hanya sekitar 4.000 orang, dengan mayoritas terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat (762 psikolog) dan DKI Jakarta (529 psikolog). Ini menciptakan "ketidakadilan geografis", di mana mereka yang paling berisiko adalah yang paling tidak memiliki akses pertolongan.
Dinding tebal stigma, yang termanifestasi dalam self-stigma dan penggunaan label seperti "kenthir" dalam budaya Jawa, semakin memperburuk keadaan, membuat jutaan orang memilih diam daripada mencari bantuan yang mereka butuhkan.
Baca juga: Kemenkes Imbau Skrining Kesehatan Jiwa Minimal Setahun Sekali
Harapan dari Akar Rumput: Menuju Jaring Pengaman Jiwa
Di tengah sistem yang timpang, harapan justru tumbuh dari akar rumput melalui model Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKBM Jiwa). Pendekatan ini secara cerdas melakukan "pergeseran tugas" (task-shifting), memberdayakan warga lokal terlatih yang disebut "kader kesehatan jiwa" untuk menjadi garda terdepan. Mereka melakukan deteksi dini, memberikan dukungan emosional, dan menjadi jembatan antara komunitas dengan Puskesmas.
Model yang terbukti berhasil seperti "Posyandu Jiwa" yang digagas di Provinsi Jawa Timur dan program pendampingan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM di Yogyakarta yang telah berjalan lebih dari enam tahun adalah cetak biru yang dapat direplikasi secara nasional. Mereka menunjukkan bahwa solusi paling efektif adalah yang terdesentralisasi, mudah diakses, dan berakar pada budaya lokal.
Untuk memutus lingkaran setan ini, diperlukan aksi kolektif yang sistemik. Pertama, bagi pemerintah, saatnya memprioritaskan dan mendanai model berbasis komunitas sebagai strategi nasional. Integrasikan layanan jiwa sebagai komponen inti di seluruh Puskesmas, bukan program sampingan. Secara paralel, atasi akar masalah ekonomi dengan memperkuat jaring pengaman sosial, seperti yang direkomendasikan Bank Dunia, dan memberantas pinjol ilegal secara agresif.
Langkah krusial lainnya adalah segera mengoperasionalkan Registri Bunuh Diri Nasional, sebuah kebijakan yang diamanatkan pada Juli 2024 sebagai respons langsung terhadap temuan studi The Lancet.
Kedua, bagi masyarakat, perluas jaringan kader kesehatan jiwa di tingkat desa dan lawan stigma melalui aksi nyata, bukan hanya kampanye. Ketiga, bagi individu dan keluarga, tingkatkan literasi kesehatan mental pribadi dan ciptakan ruang aman untuk berbicara tanpa menghakimi.
Krisis ini nyata dan mendesak, namun tidak mustahil diatasi. Dengan membangun jaring pengaman jiwa dari tingkat nasional hingga keluarga, kita dapat mengubah epidemi sunyi ini menjadi kisah ketangguhan kolektif.
Baca juga: 15 Provinsi dengan Kasus Kesehatan Jiwa Tertinggi, Mana Saja?
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang