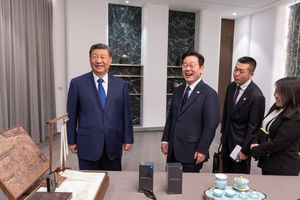Whoosh dan Ujian Anti-Korupsi Prabowo

POLEMIK seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menyeruak ke ruang publik. Dugaan adanya praktik korupsi dalam proses perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya kini menjadi bahan sorotan tajam.
Di tengah hiruk-pikuk itu, publik menunggu satu hal paling penting: bagaimana Presiden Prabowo Subianto menepati janjinya untuk tidak memberi tolerani praktik korupsi, bahkan bertekat mengejar pelakunya “hingga ke Antartika.”
Proyek Whoosh sejak awal memang ambisius. Ia digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi transportasi nasional.
Namun, di balik citra kemajuan itu, terselip problem klasik: transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan publik.
Biaya proyek yang semula diproyeksikan sekitar Rp 86 triliun, membengkak hingga lebih dari Rp 110 triliun, menimbulkan banyak tanda tanya.
Ketika pembengkakan anggaran tidak disertai dengan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban, publik wajar mempertanyakannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah melakukan penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh sejak awal 2025.
Ujian integritas pemerintahan baru
Bagi pemerintahan Prabowo, kasus ini bukan sekadar isu proyek infrastruktur. Ia merupakan ujian terhadap komitmen politik hukum presiden dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Janji untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat kini berhadapan dengan realitas kompleks: kepentingan ekonomi, politik, dan jaringan kekuasaan yang mengitarinya.
Baca juga: Menakar Konsekuensi jika Gagal Bayar Utang Whoosh
Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa hukum tidak boleh “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”
Prinsip ini sejatinya merupakan aktualisasi dari konsep rule of law sebagaimana ditegaskan oleh A.V. Dicey, yaitu bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum yang sama (Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Oxford University Press, 1959).
Artinya, penegakan hukum dalam kasus Whoosh harus menembus batas kekuasaan dan kepentingan, jika ingin tetap berada di jalur konstitusional.
Korupsi dalam proyek publik bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.
Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, keadilan hanya akan hadir jika setiap orang memperoleh haknya secara proporsional, bukan berdasarkan kekuasaan atau kedekatan politik (Aristoteles, Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, 2000).
Lebih jauh, dalam teori keadilan John Rawls, korupsi adalah bentuk ketidakadilan sistemik karena merusak asas kesetaraan peluang (fair equality of opportunity) dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjamin keadilan (A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971).