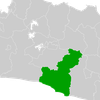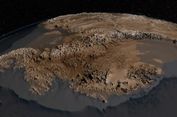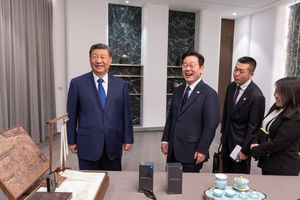BANGSA kita baru saja memperingati dua momentum penting terkait pangan dan pertanian, yaitu Hari Tani Nasional pada 24 September dan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober. Dua momentum ini dapat menjadi pengingat bahwa denyut nadi Indonesia sejak lama berakar pada tanah, alam dan lingkungan pedesaan serta pertanian.
Namun di balik gegap gempita urbanisasi dan geliat kota modern, ada jejak agraris yang diam-diam masih hidup, bukan hanya dalam ingatan kolektif, melainkan juga dalam monumen sosial berupa nama-nama kota, desa atau daerah yang kita tempati.
Menurut data Badan Informasi Geospasial, lebih dari separuh nama desa di Indonesia memiliki unsur tumbuhan atau kondisi alam dalam namanya. Ini menunjukkan betapa dalam akar agraris bangsa ini tertanam di bahasa dan identitas. Dari ujung barat hingga timur Nusantara, kita menemukan ribuan toponimi yang berakar dari kegiatan pertanian dan perkebunan.
Nama-nama seperti Kebon Jeruk, Kebon Nanas, Kampung Rambutan, Mangga Dua, Karangasem, Semarang, atau Lebak, bukanlah sekadar penanda geografis, tetapi juga penanda sejarah. Ia merekam lanskap masa lalu ketika wilayah-wilayah itu masih dipenuhi kegiatan agraris dan kegiatan pertanian.
Baca juga: Asal-usul Nama Lubang Buaya dan Alasan Jadi Tempat Pembuangan Korban G30S
Bahasa dari Alam
Sebelum peta modern digambar atau batas administratif ditetapkan, masyarakat Nusantara menamai tempat berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami. Nama bukan sekadar identitas, melainkan deskripsi ekologis dan penanda budaya. Cara menamai wilayah adalah bentuk pengetahuan lokal, semacam peta alam yang diwariskan lewat bahasa.
Semarang, misalnya, lahir dari frasa asem arang-arang, yang berarti “pohon asam yang jarang-jarang.” Dalam kisah rakyat, daerah itu dahulu merupakan lahan yang ditumbuhi pohon asam secara sporadis. Dari pengamatan sederhana terhadap vegetasi, lahirlah nama yang kelak menjadi kota besar di pantai utara Jawa.
Begitu pula Karangasem di Bali, yang menggambarkan makna karang berasal dari akar kata yang berarti tanah kering atau tanah yang agak keras, dimana pohon asam tumbuh subur. Nama-nama seperti Karangjati, Karangpucung, atau Karangnanas pun menunjukkan hal serupa, kombinasi antara kondisi tanah dan tanaman yang dominan di sana.
Jika kita menelusuri peta lama Pulau Jawa, kita akan menemukan deretan nama yang hampir selalu mengacu pada tumbuhan seperti Tegal, Kebon, Sawahan, Randublatung, Kediri (dari kediri, nama pohon kecil bergetah), Blitar (dari balitar, sejenis pohon liar). Semua mencerminkan eratnya hubungan manusia dengan alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Baca juga: Kenapa Disebut Palembang? Ini Sejarah dan Asal-usul Nama Ibu Kota Sumsel
 Penanda arah transportasi umum di Jalan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023). (KOMPAS.com/XENA OLIVIA)
Penanda arah transportasi umum di Jalan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023). (KOMPAS.com/XENA OLIVIA)Warisan Ekologi dan Ekonomi
Warisan itu tak hanya tersimpan di pedesaan. Di tengah kota besar seperti Jakarta pun, jejak agraris masih hidup dalam nama-nama wilayah. Coba perhatikan, Kebon Jeruk, Kebon Melati, Kebon Nanas, Duri Kepa, Duku Atas, Mangga Dua, hingga Kampung Rambutan. Nama-nama itu bukan hasil kreativitas modern, melainkan peninggalan masa ketika Batavia dan sekitarnya adalah kawasan pertanian yang luas.
Pada abad ke-18 dan 19, catatan kolonial Belanda menyebutkan bahwa daerah di sekitar Batavia adalah lumbung pangan kota, dimana kebun sayur, ladang padi, dan hamparan kebun buah.
“Kebon Jeruk” dulunya memang dipenuhi pohon jeruk yang ditanam penduduk Betawi dan Tionghoa. “Mangga Dua” adalah kawasan kebun mangga yang menjadi bagian dari perkebunan rakyat. “Duku Atas” menunjukkan daerah yang lebih tinggi dari “Duku Bawah,” keduanya terkenal karena buah dukunya. Nama “Kampung Rambutan” di Jakarta Timur pun lahir karena pohon rambutan yang tumbuh lebat di sekitar rumah warga.
Kini pohon-pohon itu mungkin telah berganti menjadi terminal bus, jalan tol, dan permukiman padat. Namun nama itu tetap bertahan, menjadi penanda bahwa kota ini tumbuh dari kebun, bukan dari beton.
Nama daerah berbasis pertanian mencerminkan dua hal sekaligus, yaitu kondisi ekologis dan orientasi ekonomi masyarakatnya. Ia bukan sekadar penanda alam, tetapi juga penanda aktivitas dan penghidupan.
Di Sumatra, kita mengenal “Sawah Lunto,” “Lubuk Linggau,” “Kampung Durian Runtuh,” dan “Rimbo Bujang.” “Rimbo” berarti hutan, “lubuk” adalah palung sungai tempat ikan banyak, dan “durian runtuh” menandakan musim panen buah yang menjadi sumber rezeki bagi warga.
Di Bali, nama-nama seperti Subak Abian, Tegalalang, dan Pujungan berkaitan dengan sistem irigasi dan sawah yang menjadi tulang punggung kebudayaan mereka. Di Sulawesi, kita menemukan “Kaluku” (kelapa), “Tobatibu” (kebun tebu), dan “Tomini,” dari akar kata tomi atau petani. Bahkan di Kalimantan, nama-nama seperti “Kampung Sawah,” “Bukit Nangka,” atau “Kampung Karet” menunjukkan dominasi tanaman tertentu di masa lalu.
Baca juga: Kenapa Disebut Medan? Ini Asal-usul Nama dan Sejarahnya
-
 Sejarah dan Asal Usul Nama Subang, Kota Nanas yang Berasal dari Suweng
Sejarah dan Asal Usul Nama Subang, Kota Nanas yang Berasal dari Suweng -
 Sejarah dan Asal Usul Nama Gorontalo, Hulua Lu Tola hingga Hulontalangi
Sejarah dan Asal Usul Nama Gorontalo, Hulua Lu Tola hingga Hulontalangi -
 Sejarah dan Asal-usul Nama Samarinda, Berawal dari Sama dan Rendah
Sejarah dan Asal-usul Nama Samarinda, Berawal dari Sama dan Rendah -
 Sejarah dan Asal-usul Nama Wonosobo, Berasal dari Dusun yang Didirikan Kiai Wanasaba
Sejarah dan Asal-usul Nama Wonosobo, Berasal dari Dusun yang Didirikan Kiai Wanasaba -
 Sejarah dan Asal-usul Nama Probolinggo, Maknanya Tugu Bersinar
Sejarah dan Asal-usul Nama Probolinggo, Maknanya Tugu Bersinar -
 Sejarah dan Asal-usul Nama Ponorogo, Bermula dari Cerita Raden Bathoro Katong
Sejarah dan Asal-usul Nama Ponorogo, Bermula dari Cerita Raden Bathoro Katong -
 Sejarah dan Asal-usul Nama Jepara, Kota yang Dijuluki Bumi Kartini
Sejarah dan Asal-usul Nama Jepara, Kota yang Dijuluki Bumi Kartini -
 Asal-usul Nama Garut, Berasal dari Kata Kakarut yang Artinya Tergores
Asal-usul Nama Garut, Berasal dari Kata Kakarut yang Artinya Tergores -
 Asal Usul Nama Cirebon: dari Cai dan Rebon, Air Pembuatan Terasi
Asal Usul Nama Cirebon: dari Cai dan Rebon, Air Pembuatan Terasi -
 Asal-usul Nama Kediri, Ada di Dalam Prasati Kwak hingga Prosesi Manusuk Sima
Asal-usul Nama Kediri, Ada di Dalam Prasati Kwak hingga Prosesi Manusuk Sima -
 Asal-usul Nama Malang, Bukan karena Tidak Beruntung
Asal-usul Nama Malang, Bukan karena Tidak Beruntung