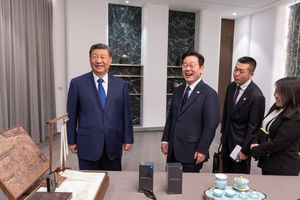BARU-BARU ini, publik dikejutkan oleh kabar tentang seorang mahasiswa Universitas Udayana yang menjadi korban dugaan perundungan di lingkungan kampus. Percakapan di media sosial memperlihatkan bagaimana olok-olok dan komentar yang tidak berempati dapat berujung pada tekanan psikologis yang mendalam.
Peristiwa ini segera memantik perhatian nasional dan membuka kembali perbincangan tentang budaya kekerasan yang masih mengintai di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
Kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk bertumbuh dan berpikir kritis, justru sering kali gagal menumbuhkan empati dan rasa hormat antarindividu. Ejekan yang dibungkus sebagai candaan menjadi bentuk kekerasan simbolik yang kerap diabaikan. Ketika lelucon yang menyakiti dianggap wajar, maka batas antara kedekatan dan kekerasan menjadi kabur.
Dalam konteks inilah, bullying mencerminkan kemunduran nilai kemanusiaan—saat martabat orang lain dipertaruhkan demi tawa sesaat. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan perundungan bukan sekadar konflik antarindividu, tetapi gejala sosial yang tumbuh dari sistem yang permisif terhadap penghinaan dan diskriminasi.
Ketika lingkungan akademik membiarkan perilaku tersebut berulang tanpa koreksi, yang sesungguhnya hilang bukan hanya rasa aman, tetapi juga nilai dasar kemanusiaan: menghargai sesama.
Tragedi sosial semacam ini semestinya menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan. Mengajarkan pengetahuan tidak cukup tanpa menumbuhkan nurani. Pendidikan yang kehilangan empati akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi tumpul secara moral. Karena itu, melawan bullying bukan sekadar menolak kekerasan, melainkan juga upaya mengembalikan kemanusiaan ke jantung pendidikan itu sendiri.
Baca juga: Kasus Bullying di Universitas Udayana, Ketua Komisi X DPR Desak Aktifkan Satgas
Normalisasi kekerasan di ruang akademik
Fenomena perundungan di kampus tidak muncul secara spontan; ini berakar dari normalisasi kekerasan dalam kehidupan akademik — ketika candaan yang menyakiti dianggap “biasa”, ketika ejekan yang merendahkan dianggap sebagai tradisi organisasi, dan ketika pengucilan sosial dianggap bagian dari dinamika kelompok.
Banyak mahasiswa menjadi takut bersuara karena khawatir dikucilkan atau dicap sebagai “pembuat masalah”. Situasi ini mengindikasikan bahwa kampus, alih-alih menjadi ruang pembebasan intelektual, justru dapat menjadi arena reproduksi kekerasan simbolik.
Konsep Symbolic Violence ala Bourdieu sangat relevan untuk memahami dinamika ini. Bourdieu menyebut bahwa kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang tersembunyi dan bekerja melalui norma, bahasa, dan budaya sehari-hari — bukan melalui kekerasan fisik langsung.
Lelucon yang merendahkan, pengucilan karena status atau latar belakang, serta komentar yang mengejek dapat dianggap sebagai manifestasi kekerasan simbolik — karena perlakuan itu memaksa korban untuk merendahkan diri atau menerima norma yang mendiskreditkan identitasnya. Kekerasan jenis ini lebih sulit dikenali dan dilawan karena sering kali diselimuti logika “kami hanya bercanda” atau “itu tradisi keakraban”.
Pun, Spiral of Silence ala Neumann membantu menjelaskan mengapa korban maupun saksi perundungan sering memilih untuk tetap diam. Teori ini menyatakan bahwa individu yang merasa opininya atau posisinya berada di minoritas cenderung menyembunyikan pendapatnya karena takut diasingkan atau dikucilkan.
Dalam lingkungan kampus yang sudah terbentuk budaya “normal” terhadap ejekan atau pengucilan, mahasiswa yang ingin menegur atau melapor dapat merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar, atau justru akan berisiko sosial. Ini menciptakan efek ganda: pelaku terus bebas karena tak ditantang, dan korban serta saksi internal menjadi bagian dari sistem kekerasan melalui diamnya.
Institusi pendidikan dalam banyak kasus memiliki aturan formal yang baik — seperti regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus — tetapi aspek efektivitas, budaya internal, dan praktik nyata sering terbengkalai.
Regulasi seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 mensyaratkan pembentukan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan termasuk perundungan. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup apabila budaya kampus masih membiarkan ejekan atau pengucilan dianggap “tradisi”.
Ketika struktur formal tidak didukung oleh perubahan kultural, maka kekerasan simbolik tetap beroperasi dan korban tetap terjebak dalam lingkaran diam dan rasa tak berdaya.
Baca juga: Koster Perintahkan Rektor Unud Bertindak Tegas dalam Kasus Bullying TAS