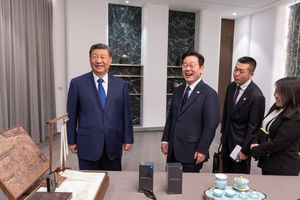JAKARTA, KOMPAS.com - Rehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia perlu memperhatikan upaya perbaikan tata kelola tambak.
Apalagi, data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2022 mengungkapkan, dari 700.000 hektar kawasan mangrove menghilang, sebanyak 631.000 hektarnya beralih fungsi menjadi tambak.
Menurut Penasehat Teknis Bidang Lingkungan dari Yayasan Hutan Biru, Yusran Nurdin Massa, untuk merehabilitasi ekosistem mangrove, perlu dicarikan banyak opsi agar bisa terintegrasi dengan tambak.
Misalnya, pengembangan model Integrated Mangrove and Sustainable Eco-culture di salah satu desa di Kabupaten Maros oleh Yayasan Hutan Biru. Model tersebut mengintegrasikan rehabilitasi ekologi mangrove dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolan tambak.
Yayasan Hutan Biru juga berupaya menggalakkan model tersebut di Kabupaten Muna dan Kabupaten Sidoarjo.
"Sangat penting untuk menjaga esensi-esensi ekologi kita yang ada di sistem pesisir dengan mangrove agar secara jangka panjang kita bisa mengadaptasi kenaikan air laut," ujar Yusran.
Model tersebut menggunakan pendekatan menghilangkan faktor gangguan pertumbuhan mangrove dengan memperbaiki sistem hidrologi.
Dalam upaya rehabilitasi mangrove, kata dia, langkah awalnya meratakan kawasan yang disiapkan dan memperbaiki sistem hidrologi. Hasilnya, terjadi sedimentasi di dalam kawasan tersebut dan aliran pasang surut mulai masuk, yang memungkinkan mangrove tumbuh secara alami.
Ketinggian substrat yang sesuai, aliran hidrologi yang memadai, dan sumber bibit yang ada menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan mangrove.
"Tugas kita adalah menghilangkan faktor gangguan," ucapnya.
Baca juga: Cegah Abrasi, QNET dan Kodim 1611/Badung Tanam 4.000 Mangrove di Pesisir Bali
Selain itu, Yayasan Hutan Biru juga mengembangkan sistem tambak dengan ekosistem mangrove di luar kawasan menjadi penyuplai kebutuhan untuk area mangrove yang juga berfungsi sebagai lahan budidaya di belakangnya.
Penanganan Degradasi Mangrove
Menurut Yusron, perlu pendekatan berbeda untuk penanganan lanskap degradasi mangrove. Misalnya, kasus 20 hektar kebun kelapa mengalami salinisasi di Kabupaten Indragiri Hilir karena hilangnya mangrove sebagai pelindung pantai.
Di Indragiri Hilir, upaya adaptasi kebun kelapa tersalisasi dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, serta masyarakat setempat.
Uji coba restorasi dilakukan dengan memperbaiki hidrologi. Setelah uji coba selama enam bulan yang gagal dengan penanaman langsung, dilakukan pemasangan batang kelapa kering untuk memblok kanal dan menciptakan aliran pasang surut alami. Hasilnya, pertumbuhan mangrove terjadi secara alami.
"Rehabilitasi mangrove bukan soal menanam, tetapi bagaimana kita mengembalikan fungsi hidrologi kawasan dan bagaimana kita bisa membaca faktor-faktor gangguannya dan fokus ke mengatasi faktor gangguannya," ucapnya.
Di sisi lain, hilangnya ekosistem mangrove juga berdampak pada erosi di pantai dan penurunan muka tanah (land subsidence). Rehabilitasi mangrove di Kabupaten Demak terhambat penurunan muka tanah akibat praktik pertambakan sejak masa kolonial Belanda.
"Makanya kalau sistem mangrove di Jawa, terutama di pantai utara Jawa, di Demak misalnya, itu (tahun) 1890 sudah ada tambak di sana. Ketika mangrovenya hilang, memori ekonomi dari sistemnya itu sulit untuk kembali," ujar Yusran.
Untuk rehabilitasi mangrove di Kabupaten Demak, kata dia, lebih sulit daripada di daerah-daerah lain seperti Kabupaten Sorong, yang memori ekonomi masyarakatnya atas sistem pemanfaatan ekosistem itu masih baik.
Baca juga: Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya