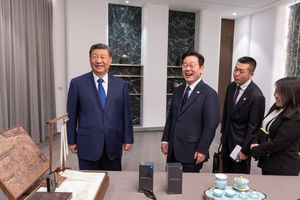Migas Masih Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi saat Tantangan EBT Belum Sepenuhnya Teratasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi pilar utama stabilitas ekonomi nasional, meskipun narasi transisi energi semakin masif. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) belum sepenuhnya teratasi.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam acara Media Training IPA bertema “Dampak Berganda Industri Hulu Migas Nasional” di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Dalam paparannya, ia menekankan bahwa peran migas dalam perekonomian masih sangat signifikan, baik dari sisi penerimaan negara maupun dampak berganda (multiplayer effect) terhadap sektor lain.
Baca juga: Genjot Investasi, SKK Migas Revisi Aturan Barang dan Jasa Hulu Migas
Komaidi menjelaskan, pada masa lalu, sektor migas menjadi lokomotif utama pembangunan.
“Dulu, penerimaan negara dari migas bisa mencapai 60 persen dari APBN dan 85 persen ekspor nasional. Dari pendapatan itu, kita membangun infrastruktur seperti jalan, bandara, hingga industri strategis,” jelas Komaidi, Selasa.
Di era kejayaan migas, produksi minyak Indonesia mencapai 1 juta-1,6 juta barrel per hari, sementara konsumsi domestik hanya 250.000-300.000 barrel.
Selisihnya diekspor dan menghasilkan devisa yang menopang perekonomian. Namun, kini produksi menurun drastis, sementara konsumsi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi.
Baca juga: TKDN Hulu Migas Naik, Ekonomi Nasional Kian Terdorong
Ketergantungan Impor dan Dampaknya terhadap Rupiah
Namun di masa kini menurut Komaidi, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah tingginya ketergantungan pada impor energi.
“Produksi minyak kita saat ini sekitar 600 ribu barrel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1,64 juta barrel. Artinya, lebih dari satu juta barel per hari masih harus diimpor,” ujar Komaidi.
Akibatnya, defisit neraca perdagangan energi semakin melebar, dan cadangan devisa nasional sebagian besar terserap untuk impor energi. Hal ini membuat nilai tukar rupiah rentan terhadap gejolak harga minyak global.
Tak hanya itu, tantangan lainnya adalah transisi energi. Meskipun transisi energi menjadi agenda global, Komaidi menegaskan bahwa EBT masih menghadapi dua tantangan utama.
Pertama, tantangan teknis akibat banyak sumber EBT yang intermittent atau bergantung pada cuaca.
“PLTS hanya optimal berproduksi antara pukul 10 pagi hingga 2 siang saat musim kemarau, sementara PLTA juga bergantung pada musim hujan dan kemarau,” jelasnya.
Kedua, tantangan ekonomi .Biaya produksi listrik dari EBT masih lebih mahal dibandingkan energi fosil.
“Jika beban biaya ini dialihkan ke konsumen, inflasi akan naik dan daya beli turun. Jika disubsidi APBN, beban fiskal akan semakin berat,” tambah Komaidi.
Baca juga: Penerapan K3 Wajib bagi Industri Hulu Migas