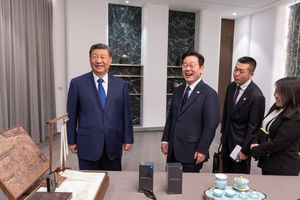PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto, dalam visi-misinya saat kampanye Pilpres 2024, menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru hingga 2029.
Namun hingga pertengahan 2025, kenyataan di lapangan masih jauh dari janji tersebut. Alih-alih tercipta lapangan kerja baru secara masif, justru gelombang PHK dan meningkatnya ketidakpastian kerja makin menguat.
Laporan World Economic Outlook yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia dalam hal tingkat pengangguran, dengan angka mencapai 5 persen, hanya sedikit di bawah China yang mencatat 5,1 persen.
Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia justru menjadi yang tertinggi, mengungguli Filipina (4,5 persen), Malaysia (3,2 persen), dan jauh di atas Vietnam serta Thailand yang tingkat penganggurannya di bawah 2 persen.
Angka itu belum mencerminkan keseluruhan masalah. Jutaan pekerja “disamarkan” ke dalam kategori informal: ojek daring, pedagang asongan, buruh harian lepas, atau pekerja paruh waktu yang hidup tanpa perlindungan sosial.
Jika pekerja informal dihitung, maka lebih dari 60 persen angkatan kerja Indonesia berada dalam kondisi kerja yang rentan—ironi di tengah jargon kemajuan dan industrialisasi.
Baca juga: Penurunan Tingkat Pengangguran dan Lonjakan Sektor Informal
Fenomena NEET (Not in Employment, Education, or Training) juga menjadi bom waktu yang luput dari radar kebijakan.
Data dari ILO dan ADB menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat NEET tertinggi di Asia Tenggara, terutama di kelompok usia muda (15–24 tahun).
Sekitar 10 juta anak muda tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak menjalani pelatihan—mereka terputus dari sistem. Mereka kehilangan arah, dan negara kehilangan kendali atas bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi.
Sementara itu, gelombang PHK terus menggerus rasa aman kerja. Industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki melakukan efisiensi besar-besaran. Start-up digital tumbang satu per satu.
Bahkan sektor yang selama ini dianggap relatif aman—seperti perbankan, media, dan logistik—mulai melakukan rasionalisasi.
Dalam dua tahun terakhir, ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Namun, negara tampak hanya mencatat, tanpa satu pun aktor institusional yang secara khusus bertugas mencegah atau memulihkan krisis ketenagakerjaan secara sistemik.
Di berbagai kota, job fair berubah menjadi drama sosial. Ribuan pelamar memadati lokasi bursa kerja hanya untuk menemukan antrean panjang, informasi yang tidak jelas, dan jumlah lowongan yang tidak sebanding dengan pelamar.
Di Bekasi, kericuhan sempat pecah karena jumlah peserta melebihi kapasitas lokasi.
Di berbagai daerah, pelamar harus datang sejak subuh demi memastikan formulir pendaftaran tidak habis. Job fair menjadi simbol ironi: ia dirancang untuk memberi harapan, tapi justru memperlihatkan betapa terbatasnya peluang yang tersedia.
Gejolak sosial pun mulai menyeruak ke permukaan. Viralnya tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar luapan frustrasi di media sosial, melainkan sinyal bahwa semakin banyak anak muda kehilangan kepercayaan terhadap negeri ini sebagai ruang hidup yang layak dan memberi harapan.
Baca juga: Daya Beli Melemah: Saatnya Pajak Pro-Kelas Menengah
Bekerja ke luar negeri pun tak kunjung difasilitasi negara dengan sistem yang memudahkan dan bermartabat.
Mereka yang pergi bukan sedang mengejar mimpi indah, apalagi kekayaan. Mereka pergi karena didesak keadaan. Sebab di tanah kelahiran sendiri, peluang untuk hidup layak kian menyempit. Ini bukan soal ambisi—ini soal bertahan hidup. Mereka hanya ingin bekerja.
Di satu sisi, pemerintah kerap menyampaikan klaim keberhasilan dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan melalui program vokasi dan padat karya.
Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, melaporkan telah meningkatkan kompetensi ratusan ribu orang melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi.
Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa sebanyak 3,59 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025, mengacu pada data BPS yang dirilis pada Mei 2025.
Angka ini diklaim turut mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,76 persen—terendah sejak krisis ekonomi 1998.
Namun, laporan-laporan semacam ini umumnya lebih menonjolkan output administratif—seperti jumlah peserta pelatihan—ketimbang outcome strategis berupa penyerapan tenaga kerja formal yang berkelanjutan.
Tanpa adanya audit independen dan mekanisme verifikasi transparan, publik sulit menilai seberapa besar dampak riil dari program-program tersebut terhadap ketahanan kerja nasional.
Kementerian Perindustrian pun sempat mengklaim bahwa mayoritas lulusan vokasi mereka terserap ke sektor industri. Namun, data tersebut bersifat sektoral, terbatas pada lembaga binaan langsung, dan tidak mencerminkan efektivitas program pelatihan secara nasional.
Klaim optimistis juga datang dari sektor hilirisasi. Dalam Human Capital Summit (Juni 2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa proyek hilirisasi dan transisi energi akan menciptakan sekitar 6,2 juta lapangan kerja langsung hingga 2030—meliputi sektor ketenagalistrikan, mineral, batu bara, dan kendaraan listrik.
Saat menanggapi kritik publik, ia bahkan melontarkan pernyataan “jangan kufur nikmat”—seolah optimisme saja cukup menggantikan kebutuhan akan data yang terverifikasi.
Baca juga: Kufur Nikmat dan Derita Pencari Kerja
Jika ditarik secara keseluruhan, hingga pertengahan 2025 belum ada satu pun dari klaim sektoral tersebut yang disertai audit independen atau data publik yang dapat memverifikasi secara konkret berapa banyak lapangan kerja riil yang benar-benar tercipta.
Pada akhirnya, baik program vokasi maupun proyek hilirisasi menghadapi tantangan mendasar yang serupa: minimnya transparansi, lemahnya pengukuran dampak, dan absennya akuntabilitas kelembagaan.
Masyarakat tidak disuguhi metrik yang jelas antara program yang dijalankan dan jumlah pekerjaan yang benar-benar tercipta.
Tanpa perbaikan menyeluruh dalam tata kelola, seluruh upaya penciptaan kerja rentan terjebak dalam rutinitas birokrasi yang hampa—jauh dari solusi struktural atas krisis ketenagakerjaan nasional.
Lebih dari itu, publik terus menyaksikan pola yang berulang: gelombang pelatihan tanpa kepastian kerja, gelombang PHK yang merajalela, dan akhirnya gelombang kekecewaan yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Janji berubah menjadi ilusi. Ilusi berubah menjadi krisis. Dan krisis perlahan menjelma menjadi normal baru yang melelahkan secara sosial dan psikologis.
Janji Prabowo untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga 2029 bukan sekadar angka besar. Ia adalah janji struktural yang membutuhkan kepemimpinan, desain kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Persoalannya bukan hanya “berapa?”, melainkan juga “bagaimana?” dan “oleh siapa?”.
Ini bukan soal kegagalan satu presiden. Fenomena melesetnya janji penciptaan kerja adalah pola sistemik yang telah berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Janji membuka lapangan kerja telah menjadi semacam ritual politik: wajib diucapkan saat kampanye, tapi dibiarkan tanpa mekanisme eksekusi begitu pemilu usai.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya