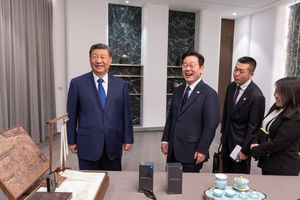Universitas Riset Indonesia di Antara Idealisme dan Realisme Struktural

TULISAN Prof. Terry Mart di Harian Kompas, 27 Oktober 2025, mengenai keniscayaan universitas riset (Research University) murni di Indonesia membuka diskusi penting tentang masa depan perguruan tinggi nasional yang saat ini lebih berfokus sebagai Universitas Pengajaran (Teaching University).
Saya mengapresiasi analisis komprehensif beliau yang menyoroti keberagaman model universitas riset global, mulai dari University of Cambridge dengan 38% mahasiswa pascasarjana hingga National University of Singapore (NUS) dengan 27%, dan University of Tokyo dengan 50% namun hanya 10% dosen internasional.
Tetapi, izinkan saya memperdalam pembahasan dengan menambahkan perspektif kritis mengenai tiga pilar struktural yang sesungguhnya menjadi akar persoalan: sistem promosi dosen, otonomi kampus, dan peran pemerintah versus swasta.
Sistem Promosi: Mengukur Kuantitas, Kehilangan Kualitas
Problem fundamental universitas riset Indonesia terletak pada sistem promosi dosen yang counterproductive. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur internasional, universitas riset sejati membedakan diri bukan hanya melalui volume publikasi, tetapi melalui dampak dan kepemimpinan intelektual dalam bidangnya.
Studi Times Higher Education (2024) menekankan bahwa kualitas riset tidak hanya diukur dari jumlah sitasi, melainkan dari "research influence", seberapa jauh riset tersebut diakui dan dibangun oleh penelitian paling berpengaruh di dunia.
Sayangnya, sistem angka kredit kita justru mendorong dosen mengejar kuantitas publikasi untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan menghasilkan riset berdampak tinggi yang menjawab tantangan global.
Ironinya, seperti diungkapkan Prof. Terry Mart, banyak dosen Indonesia masuk dalam 2% peneliti paling berpengaruh versi Stanford. Namun, pencapaian individual ini tidak diterjemahkan menjadi transformasi institusional karena sistem promosi yang birokratis. Dosen terjebak dalam paradoks: mereka harus produktif secara individual untuk promosi, tetapi institusi tempat mereka bekerja tidak menyediakan ekosistem yang mendukung riset berkualitas tinggi.
Dampak riset ditujukan sebagai "efek pada, perubahan atau manfaat terhadap ekonomi, masyarakat, budaya, kebijakan publik atau layanan, kesehatan, lingkungan atau kualitas hidup, di luar akademia." Sistem ini memaksa universitas untuk menunjukkan bagaimana riset mereka memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar akumulasi angka publikasi.
Di sana, promosi ke posisi profesor penuh mempertimbangkan kepemimpinan dalam komunitas ilmiah global, bukan sekadar jumlah publikasi di jurnal terindeks.
Baca juga: 13 Universitas Riset Ilmiahnya Diragukan, Kemendikti: Indonesia Masih Belajar
Otonomi Kampus: Terkekang Regulasi, Kehilangan Inovasi
Perdebatan tentang universitas riset versus universitas pengajaran di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi bergantung pada otonomi institusional. Universitas riset memerlukan fleksibilitas dalam merekrut peneliti berkelas dunia, mendesain kurikulum inovatif, dan mengalokasikan sumber daya secara strategis. Namun, universitas di Indonesia masih terkekang regulasi kaku dari pemerintah, mulai dari pengadaan, rekrutmen, hingga pengelolaan keuangan.
Altbach dan Salmi dalam studi World Bank (2011) menegaskan bahwa universitas riset yang sukses memerlukan karakteristik kunci: berada di puncak hierarki akademik dalam sistem pendidikan tinggi yang terdiferensiasi dengan dukungan yang memadai, kompetisi minimal dari lembaga riset non-universitas kecuali memiliki koneksi kuat dengan universitas, dan pendanaan lebih besar dibanding universitas lain untuk menarik staf dan mahasiswa terbaik serta mendukung infrastruktur riset.
Tanpa otonomi, universitas Indonesia tidak dapat memenuhi prasyarat dasar ini. Akibatnya, universitas kehilangan kemampuan untuk berinovasi. Ketika NUS atau Cambridge dapat dengan cepat merekrut superstar researcher dari berbagai negara dengan paket kompensasi kompetitif, universitas Indonesia harus melalui birokrasi panjang yang sering kali membuat kandidat terbaik memilih institusi lain.
Ketika MIT dapat segera membangun laboratorium baru untuk bidang riset emerging, universitas di Indonesia harus menunggu persetujuan berlapis yang memakan waktu bertahun-tahun.
Prof. Terry Mart menyinggung bahwa universitas riset tidak seragam dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional. Saya setuju. Namun, penyesuaian tersebut hanya mungkin jika universitas memiliki otonomi penuh untuk mendesain modelnya sendiri. Tanpa otonomi, semua universitas akan terjebak dalam satu format yang sama—teaching institution dengan beban administratif berlebih.
Baca juga: 10 Universitas Terbaik di Indonesia Berdasarkan THE Impact 2025, Unair Ungguli UI dan UGM
Peran Pemerintah versus Swasta: Dilema Pendanaan Riset
Ketergantungan pada pendanaan pemerintah menjadi bottleneck ketiga. Sebagaimana diungkapkan Prof. Terry Mart, di negara maju universitas diperbolehkan menarik dana overhead dari proyek riset pemerintah, praktik yang belum diizinkan di Indonesia. Ini menciptakan situasi absurd: universitas diharapkan menghasilkan riset berkualitas tinggi, tetapi tidak diberi instrumen finansial untuk mendukung infrastruktur riset.