
Dasyatnya Kontestasi Kuasa di Balik Bola Bundar

SEPAK bola kini lebih dari sekadar olahraga. Ia menjadi panggung tempat kekuasaan bekerja dengan cara yang tidak selalu kasat mata.
Di balik sorak penonton melalui layar televisi dan linimasa media sosial, berlangsung pertarungan simbolik antara federasi, pelatih, pemain, jurnalis, komentator, dan jutaan warganet yang menganggap diri mereka pemilik moral dari “tim nasional.”
Fenomena ini mencapai puncaknya ketika publik digital menekan federasi untuk memecat pelatih. Dalam hitungan hari, bermunculan tagar “penolakan” atau sebaliknya “pengidolaan” yang cepat berubah menjadi kekuatan politik simbolik.
Kekuatan tersebut sampai mengguncang otoritas sepak bola nasional, hingga Istana Kepresidenan pun ikut bersuara tentang sepak bola.
Peristiwa itu memperlihatkan betapa dahsyatnya kontestasi kekuasaan yang bekerja di balik bola bundar.
Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan relasi yang menyebar melalui wacana dan praktik sosial pada berbagai level atau tingkatan dan lapisan (Maring, 2022: Kekuasaan yang dinamis dan tersebar).
Baca juga: Mimpi Piala Dunia Kandas dan Sesat Pikir Alex Pastoor
Kekuasaan tidak lagi bersumber dari menara tinggi, tetapi beredar di antara kita, melebur dalam percakapan, unggahan, dan komentar daring.
Sepak bola Indonesia menjadi contoh paling aktual dari pergeseran lanskap kekuasaan: dari ruang rapat federasi menuju ruang digital yang dikendalikan oleh opini publik.
PSSI memang memegang otoritas formal atas arah tim sepak bola nasional. Namun, legitimasi simbolik kini juga bergantung pada publik digital yang menilai performa, memantau kebijakan, dan menafsirkan strategi permainan.
Dalam perspektif Foucault, ini adalah bentuk governmentality baru: cara masyarakat memerintah balik institusi melalui pengawasan kolektif.
Jika dulu pemain diawasi pelatih, maka kini federasi pun diawasi oleh netizen yang tak pernah tidur dalam jumlah yang sangat banyak.
Kita kini ibarat hidup dalam panoptikon terbalik, ia tidak lagi hanya diawasi dan dikontrol dari satu menara tunggal di titik pusat.
Kini semua pentas di lapangan hijau dan suara-suara dari menara para pemegang otoritas seolah tidak luput dari tatapan tajam publik. Teknologi informasi dan digitalisasi kini menjadi alat pengawasan paling efektif terhadap kekuasaan formal.
Namun, yang menarik bukan hanya siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan bekerja (Maring, 2010: Bagaimana kekuasaan bekerja di balik konflik dan perlawanan).
Media sosial menghadirkan arena baru tempat kekuasaan dan resistensi saling bertautan dan berkontestasi.


























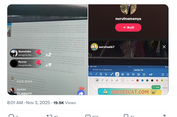




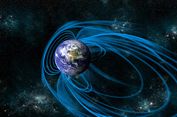





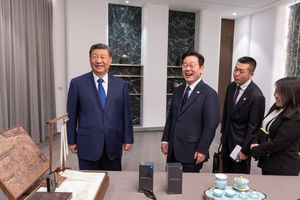






![[POPULER TREN] Dampak Pelegalan Umrah Backpacker | Aturan Baru Bawa Powerbank di KA](https://asset.kompas.com/crops/nMcRCBuTodP3Pvo_MfqwSIUWMAk=/153x434:1792x1527/95x95/data/photo/2025/10/24/68fb7db0a0a90.jpg)








