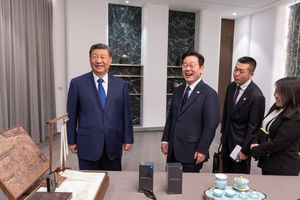Kawasan Tebu Nasional dalam Kekosongan Implementasi

DALAM sejarah kebijakan pertanian kita, gairah untuk mengumumkan program selalu lebih membara daripada kesanggupan mengeksekusinya.
Setiap kali pemerintah merilis rencana baru, dari roadmap hulu-hilir hingga penetapan kawasan tebu nasional, semangat itu berapi-api di awal, lalu menghilang saat implementasi.
Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang ditetapkan sebagai Kawasan Tebu Nasional pada akhir 2024, adalah contohnya.
Hampir setahun berlalu, tetapi belum juga terbit peraturan menteri, petunjuk teknis, ataupun langkah operasional yang menjelaskan apa arti status “nasional” tersebut bagi petani, pemerintah daerah, maupun investor.
Baca juga: Menyambut Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional
Akibatnya, pemerintah daerah hanya bisa menunggu arah yang tak kunjung jelas. Keputusan datang dari pusat tanpa penjelasan, tanpa dukungan, dan tanpa ruang bagi mereka untuk menafsirkan sendiri.
Bukan karena daerah tidak ingin bergerak, tapi semata karena kebijakan itu memang tak memberi pijakan untuk melangkah.
Fenomena no action, talk only ini bukan cuma masalah di pusat. Di daerah, birokrasi kerap pasif—menunggu “perintah resmi” sebelum bertindak. Ironisnya, semakin banyak keputusan strategis dibuat dari atas, semakin terbatas ruang gerak di bawah.
Zaman sudah berganti, tetapi pola kebijakan kita tak banyak berubah. Banyak keputusan hari ini sesungguhnya hanya mengulang sistem yang sudah berusia lebih dari seabad.
Sejak masa tanam paksa hingga era otonomi daerah, negara selalu lebih rajin mengumumkan program baru ketimbang membangun cara untuk menjalankannya. Semangat mengatur selalu lebih besar daripada kemauan mengeksekusi.
Sejarawan Ulbe Bosma (2013) mencatat bahwa bahkan setelah kemerdekaan, industri tebu Indonesia masih memperlihatkan banyak kemiripan dengan masa kolonial. Polanya tetap bertumpu pada hubungan antara elite desa dan pabrik gula.
Dalam banyak hal, reformasi pertanian sejak 1970-an hanyalah bentuk baru dari sistem tanam paksa dalam versi modern. Karena lahir dari tradisi yang terbiasa memerintah, bukan mendengarkan, kebijakan dari pusat pun kerap mandek begitu tiba di lapangan.
Selama daerah tidak mengartikulasikan kepentingannya sendiri dan membangun tekanan politik lokal, setiap program “nasionalisasi tebu” hanya akan menjadi bagian dari warisan panjang yang disebut Bosma sebagai Asian plantation: industri besar yang tampak merdeka, tapi secara struktural masih kolonial.
Pola seperti ini bukan hanya warisan kolonial, tetapi juga bagian dari jebakan modernisasi yang disebut Erik Reinert (2007) sebagai imitative development—negara yang sibuk meniru bentuk kebijakan maju tanpa membangun struktur produktif di bawahnya.
Akibatnya, kebijakan terlihat modern di atas kertas, tapi kosong di lapangan karena tidak didukung proses belajar dan lembaga produksi yang hidup.
Dalam hal ini mari kita lihat keberhasilan negeri orang. Negeri Samba Brasil, misalnya, tak berhenti pada penetapan kawasan tebu; mereka membangun seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir—dari riset benih, investasi pabrik, hingga pemanfaatan limbah tebu menjadi sumber energi terbarukan (renewable energy).
Setiap pabrik di sana menghasilkan listrik sendiri dari bagasse, limbah tebu yang dibakar dimanfaatkan untuk menciptakan uap dan tenaga.
Langkah ini bukan hanya memperkuat kemandirian energi, tapi juga menumbuhkan perekonomian lokal.
Sebaliknya di Indonesia, kebijakan sering berhenti di tataran administratif. Penetapan kawasan tebu nasional di Dompu tanpa petunjuk teknis dan dukungan investasi memperlihatkan bagaimana keputusan pusat gagal menjadi motor bagi inisiatif di daerah.
Bukan ide yang kurang, melainkan kemauan eksekusi. Setiap kali kebijakan diumumkan, pemerintah tampak lebih sibuk dengan panggung peresmian ketimbang memastikan sistem berjalan.
Padahal, jika pemerintah daerah diberi ruang untuk berkreasi—mengembangkan kemitraan dengan investor, koperasi, dan universitas lokal—hilirisasi tebu tidak perlu menunggu aba-aba dan komando dari Jakarta.
Baca juga: Whoosh Bukan Investasi Sosial