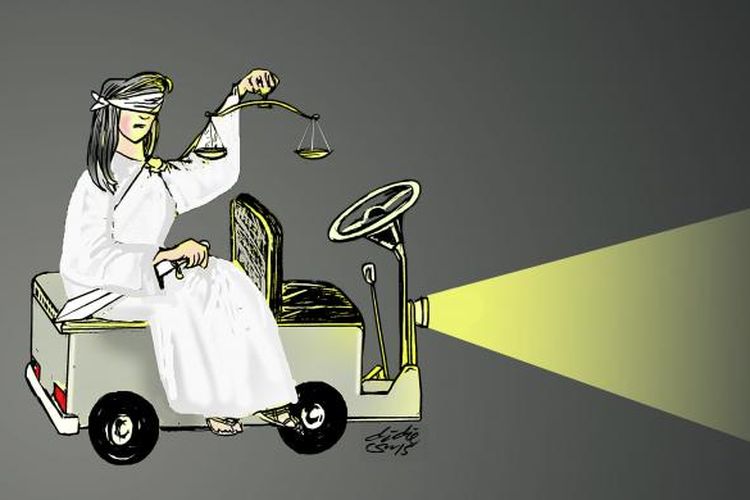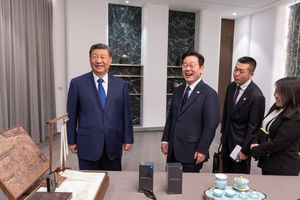Berhukum tapi Tak Bernurani

HUKUM sering kali tampak seperti menara gading. Ia menjulang tinggi dalam pasal-pasal, tetapi terlalu jauh dari bumi tempat rakyat berpijak.
Di dalam gedung-gedung pengadilan yang menjulang, hukum dibacakan dengan suara mantap, palu diketuk, dan putusan dijatuhkan. Namun, tak sedikit dari kita yang bertanya lirih: di mana letak nurani dalam putusan itu?
Nurani, kata yang kini kerap dianggap barang mewah dalam praktik hukum. Padahal, hukum sejatinya adalah anak kandung dari moralitas publik.
Hukum bukan hanya sistem logika, bukan pula sekadar kalkulasi prosedural. Ia adalah produk dari pergulatan nilai, rasa keadilan, dan cita-cita kemanusiaan.
Namun hari ini, ketika kita menyaksikan putusan yang sah secara hukum tetapi melukai rasa keadilan masyarakat, kita berhak bertanya: untuk siapa hukum ditegakkan?
Hukum sebagai kekuasaan yang membisu
Satjipto Rahardjo mengajarkan kepada kita bahwa hukum harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan, bukan sekadar teks atau doktrin.
Namun dalam praktiknya, hukum telah lama digiring ke ruang sempit: menjadi teknis, prosedural, dan steril dari nilai-nilai.
Baca juga: Usul Sesat MPR Tafsirkan Konstitusi
Ketika seorang perempuan korban kekerasan seksual justru dijatuhi hukuman karena dianggap mencemarkan nama baik pelaku, kita tidak sedang menyaksikan hukum, melainkan kekuasaan yang menyaru sebagai hukum.
Ketika seorang anak miskin mencuri sandal jepit dan divonis, tetapi korporasi perusak lingkungan hanya dikenakan denda yang bisa dibayar dengan sekali rapat direksi, kita sedang menyaksikan ketimpangan yang dilembagakan.
Hukum yang dibangun tanpa nurani adalah hukum yang mengabaikan realitas. Ia menjadi kekuasaan yang membeku, bukan pembebas. Ia menjadi pedang yang hanya tajam ke bawah.
Nurani bukan sekadar empati; ia adalah panduan moral terdalam yang membimbing manusia membedakan yang benar dan yang keliru.
Dalam filsafat hukum, nurani tak berdiri sendiri. Ia melekat dalam konsep keadilan substantif—yang tak selalu identik dengan apa yang tertulis dalam undang-undang.
Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman, pernah mengingatkan kita melalui formulanya yang terkenal, bahwa dalam kondisi ekstrem, keadilan harus mengalahkan hukum positif.
Ia berkata, “Hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum.” Maka, ketika aparat penegak hukum bersikukuh menjalankan hukum positif yang jelas-jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, mereka bukan sedang menegakkan hukum—melainkan sedang menegakkan ketidakadilan yang dilegalkan.
Nurani-lah yang menjadi jembatan antara teks hukum dan realitas sosial. Tanpa nurani, hukum menjadi benda mati. Ia bisa dibaca, tetapi tak bisa dirasakan.