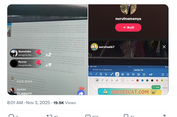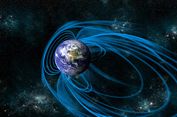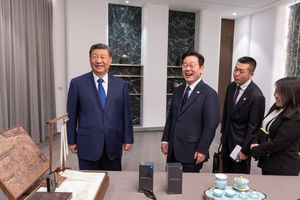Workslop, Output Semenjana AI, dan Sampah Digital

SURVEI Sharing Vision 2025 menunjukkan bahwa 69,8 persen responden di Indonesia memandang AI (Akal Imitasi) sebagai pendorong percepatan tugas rutin. Ini pandangan yang dapat menginspirasi bagi bangsa muda seperti kita.
Namun, laporan Stanford AI Index 2025 mengingatkan, di balik lonjakan adopsi AI (dengan investasi global mencapai 252,3 miliar dollar AS pada 2024), ada risiko seperti overfitting dan output berkualitas rendah yang dapat mengurangi produktivitas.
AI memang memantik kegairahan intelektual dan selalu menghangatkan semangat kritik. Immanuel Kant menggoncang dunia pasca-Aufklarung dengan Kritik pada Akal Murni (Kritik der reinen Vernunft).
Ia demikian cermat mencoba mencari batas-batas epistemik pengetahuan yang masih bisa dipahami rasio manusia.
Tradisi kritik intelektual Kant ini masih hidup hingga kini. Kali ini, dunia diguncang dengan narasi Singularity AI.
Apa itu singularity AI? Suatu kondisi, yang menurut Ray Kurzweil, di mana AI menjadi lebih cerdas dari Einstein dan umumnya seluruh umat manusia.
Maka berduyun-duyun pemikir dan filsuf seperti John Searle (yang wafat September 2025), Harry Frankfurt, Noam Chomsky, hingga Mira Murati (mantan CTO dan CEO sementara OpenAI) melancarkan berbagai kritik terhadap “akal imitasi murni”—sebuah gerakan intelektual yang mempertanyakan apakah AI benar-benar memahami, atau sekadar meniru kecerdasan manusia.
Baca juga: Bolehkah AI Mencalonkan Diri dalam Pilpres 2029?
Di antara kritik terkini adalah workslop. Apa itu workslop? Yaitu konten kerja yang dihasilkan AI, tampak menarik dan efisien di luar, tetapi kurang mendalam, mirip dengan bangunan indah tanpa fondasi yang kuat.
Istilah ini muncul dari penelitian Stanford Social Media Lab dan BetterUp Labs, yang menggambarkan gelombang dokumen, email, serta laporan yang tampak "cukup baik", tapi kurang mampu mendorong kemajuan sejati, justru menumpuk sebagai limbah digital di ruang kerja kita.
Bayangkan situasi di mana seorang rekan menyajikan laporan analisis pasar dengan bangga, tapi ternyata isinya penuh dengan data yang tidak akurat atau ungkapan umum yang kurang berguna.
Persoalan workslop bukan hanya soal efisiensi yang terganggu; ini mencerminkan tantangan bagi potensi kita sebagai manusia. Workslop tidak lain adalah output semenjana. Bahasa lainnya adalah sampah digital.
Sahabat kami dalam grup diskusi Filsafat Way Of Life yang kami ampu, Doktor Budi Sulistyo, telah meramalkan merebaknya sampah digital atau workslop ini sejak awal mula booming LLM pada 2023 lalu.
Beliau berpendapat, ketika sampah digital ini terus-menerus diumpankan kembali ke berbagai AI, hasilnya hanyalah sampah digital dalam level yang lebih tinggi—dan siklus ini akan berulang tanpa henti.
Penulis pribadi sangat tertarik untuk mendalami bidang ini, bahkan mencoba memodelkannya secara matematis dengan teori ketidakstabilan dari AM. Lyapunov, bidang yang saya dan Kelompok Keahlian Kendali dan Komputer di STEI ITB tekuni.
Menariknya, ketika isu tentang output semenjana, sampah digital, atau workslop ini masih menjadi bagian dari agenda peta jalan penelitian kami, justru Stanford dan Harvard—dua think tank global terkemuka dari Amerika Serikat—sudah lebih dulu merilis hasil penelitian yang amat mengejutkan.
Workslop di balik layar
Fenomena workslop bukanlah cerita fiksi dystopia; ia sudah menjadi bagian dari rutinitas kantor kita.
Seperti yang dijelaskan dalam suatu artikel yang dimuat di Australian Financial Review, workslop timbul ketika AI menghasilkan konten yang tampak seperti hasil kerja berkualitas, tetapi sering memerlukan perbaikan ulang.
Di lingkungan kerja, hal ini berarti tim yang mengandalkan alat seperti ChatGPT untuk menyusun proposal, membuat presentasi, sering kali hanya menghasilkan dokumen yang memadai, tapi jauh dari istimewa, bahkan hasil semacam ini sering memaksa rekan kerja atau manajer untuk membongkar kembali asumsi yang salah atau bahkan menyusun ulang pekerjaan dari awal.
Baca juga: Welcome GPT-5: Penciptanya Malah Bertanya, Apa yang Sudah Kita Lakukan?
Meskipun penggunaan AI di tempat kerja telah berlipat ganda sejak 2023, Laporan dari MIT Media Lab menyoroti bahwa 95 persen organisasi belum melihat pengembalian investasi (ROI) yang nyata.
Alasannya? Workslop ini dapat mengganggu produktivitas—bukan dengan memperlambat proses, melainkan dengan menciptakan kesan kemajuan yang semu.
Dampaknya terasa jelas: berdasarkan survei McKinsey (2023), 65 persen organisasi secara rutin menggunakan GenAI untuk pekerjaan seperti menyusun memo atau merangkum data.
Namun, alih-alih mempercepat efisiensi, keluaran AI yang sering generik dan dangkal justru menimbulkan ‘AI fatigue’—kelelahan kolektif ketika tim harus berhadapan dengan arus konten repetitif yang terasa low-effort.
Di Indonesia, survei Sharing Vision 2025 (Mei-Juni 2025, melibatkan 5.755 responden) mengungkap optimisme yang tinggi: 84 persen pengguna mengandalkan model bahasa besar seperti ChatGPT, dengan 58,4 persen merasakan peningkatan efisiensi kerja, 61,5 persen melihat AI membantu dalam menemukan ide saat buntu, dan 51,3 persen menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.
Namun, sisi gelapnya adalah lebih dari 5 persen netizen menggunakan AI lebih dari 4 jam sehari. Hal ini berpotensi melemahkan pemikiran kritis dan kemampuan problem solving, sebagaimana terlihat dalam hasil survei yang diselenggarakan oleh Hong Kong Academy for Gifted Education, yang relevan dengan konteks kita.