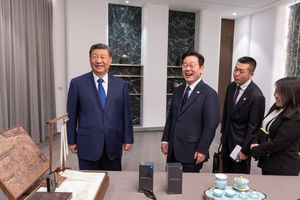Pertanian Motor Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Data per Agustus 2023 mencatat jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 7,86 juta orang atau 5,33 persen angkatan kerja.
Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,57 persen dari total penduduk (sekitar 24,06 juta orang) pada September 2024, angka terendah dalam satu dekade.
Meski capaian ini menggembirakan, kenyataannya masih ada puluhan juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kemiskinan terkonsentrasi di wilayah perdesaan, 11,34 persen penduduk desa tergolong miskin, jauh lebih tinggi dibanding 6,66 persen di perkotaan.
Fakta ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan erat kaitannya dengan kondisi pedesaan dan infrastruktur pendukung.
Dalam konteks ini, revitalisasi sektor pertanian, sebagai motor utama ekonomi pedesaan dapat menjadi kunci penting untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus mengentaskan kemiskinan.
Secara keseluruhan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Pada awal 2025, sekitar 28,5 persen total pekerjaan berada di sektor ini. Di antara subsektornya, perkebunan menempati posisi sentral.
Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan terdapat 10,8 juta rumah tangga usaha perkebunan di Indonesia, artinya puluhan juta penduduk menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.
Dari sisi ekonomi makro, kontribusi perkebunan juga signifikan, yaitu menyumbang sekitar 3,6 persen PDB nasional pada 2021 dan menjadi sumber devisa andalan.
Sepanjang 2022, ekspor produk pertanian Indonesia mencapai Rp 640 triliun, di mana 97 persen di antaranya berasal dari komoditas perkebunan.
Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa pun sangat terasa. Industri sawit, misalnya, mampu menyerap 16,2 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.
Sekitar 40 persen lahan sawit nasional justru dikelola oleh 2 juta petani swadaya, yang pendapatannya bisa mencapai 5–10 kali lipat lebih tinggi dibanding petani komoditas pangan lain.
Studi bahkan menemukan bahwa setiap kenaikan 10 persen produksi sawit mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7,7 persen, dengan laju penurunan kemiskinan lebih cepat di daerah sentra sawit.
Hal serupa juga berlaku untuk komoditas lain seperti karet, kopi, kakao, dan teh yang menjadi andalan daerah masing-masing.
Singkatnya, subsektor perkebunan merupakan fondasi ekonomi perdesaan, yang bila dikelola optimal, dapat memperkecil kesenjangan desa-kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan nasional.
Kendala klasik
Meski berperan strategis, sektor perkebunan rakyat menghadapi berbagai kendala klasik yang menghambat potensi maksimalnya.
Produktivitas rendah menjadi tantangan utama. Banyak tanaman perkebunan masih dikelola secara tradisional dengan pohon-pohon tua atau varietas kurang unggul, sehingga hasil per hektare jauh di bawah potensi.
Sebagai gambaran, produktivitas rata-rata kebun kelapa sawit rakyat hanya sekitar 3–4 ton minyak per hektar, padahal dengan bibit unggul bisa mencapai 6–8 ton.
Rendahnya adopsi teknologi modern, minimnya mekanisasi, serta kurangnya penyuluhan pertanian turut berkontribusi pada stagnannya produktivitas.
Regenerasi petani juga menjadi isu tersendiri. Generasi muda kurang tertarik bertani akibat hasil yang kecil dan kerja berat, sehingga inovasi berjalan lambat.
Kendala berikutnya terkait kepemilikan lahan dan skala usaha. Mayoritas petani perkebunan tergolong petani kecil (smallholders) dengan lahan sempit, sering kali di bawah dua hektar per keluarga.
Skala yang terbatas ini menyulitkan upaya intensifikasi dan efisiensi ekonomi.
Di sisi lain, terdapat ketimpangan struktural, dimana sebagian besar lahan luas dikuasai perusahaan besar (swasta maupun BUMN), sementara jutaan petani kecil hanya menggarap lahan marginal.
Dari total sekitar 14 juta hektar kebun sawit nasional, 43 persen dikelola petani rakyat, sementara sisanya korporasi besar.
Kondisi ini menimbulkan kesenjangan produktivitas dan pendapatan. Lebih jauh lagi, banyak pekebun kecil tidak memiliki legalitas atas lahan atau lahannya masuk kawasan hutan, sehingga sulit mendapat bantuan pemerintah maupun akses kredit formal, sekaligus rawan konflik agraria.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah akses pasar dan rantai nilai. Petani perkebunan sering kali berada di posisi lemah dalam rantai pasok.
Mereka bergantung pada tengkulak atau perusahaan besar, sehingga harga jual di tingkat petani relatif rendah. Panjangnya rantai pemasaran menggerus margin keuntungan.
Petani karet dan kopi, misalnya, kerap mengeluhkan harga jatuh di tingkat desa, padahal komoditas bernilai tinggi di pasar ekspor.
Ketidakstabilan harga global, seperti fluktuasi CPO atau anjloknya karet dunia, langsung memukul pendapatan petani yang tidak memiliki perlindungan harga.
Ditambah lagi, disparitas infrastruktur membuat harga di daerah terpencil jauh lebih rendah dibanding sentra utama di Jawa atau Sumatra.
Untuk menjadikan subsektor perkebunan sebagai motor penciptaan kerja sekaligus pengentas kemiskinan, ada beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh.
Di antaranya adalah peremajaan tanaman dengan bibit unggul dan teknologi modern, diversifikasi komoditas unggulan agar petani tidak tergantung satu produk, serta perluasan akses pembiayaan dan insentif.
Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau korporasi dapat meningkatkan posisi tawar mereka, sementara hilirisasi dan pembangunan industri pengolahan di tingkat lokal akan menambah nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan menjaga agar keuntungan lebih banyak tinggal di desa.
Praktik baik pemberdayaan petani
Upaya revitalisasi dan pemberdayaan perkebunan rakyat mulai menunjukkan hasil di berbagai daerah. Sejumlah praktik baik membuktikan bahwa dengan dukungan kelembagaan, pasar, dan kebijakan yang tepat, petani mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menembus rantai pasok global.
Salah satu contohnya datang dari Manggarai Timur, NTT, di mana petani kopi robusta dan arabika yang tergabung dalam koperasi berhasil menembus pasar ekspor hingga Eropa.
Kualitas kopi Flores yang dikelola secara kolektif diminati pembeli dari Belanda, Jerman, hingga Italia.
Dampaknya signifikan, harga beli di tingkat petani melonjak menjadi Rp 29.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibanding penjualan ke tengkulak lokal.
Keberhasilan ini tercapai berkat pendampingan mutu, promosi, serta dukungan pemerintah daerah dalam sertifikasi dan kemitraan dagang.
Kisah serupa hadir dari Jawa Barat, ketika lima koperasi petani kopi berkolaborasi membentuk PT Java Preanger Lestari Mandiri (JPLM).
Dengan dukungan Kementerian Pertanian, korporasi ini tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengelola pengolahan, branding, hingga aktif mengikuti pameran internasional seperti Istanbul Coffee Expo.
Pemerintah membantu dengan akses modal, bibit unggul, dan unit pengolahan, sehingga produktivitas meningkat dan produk olahan kopi dapat dijual dengan harga premium.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, koperasi petani sawit berhasil mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit (mini CPO mill) milik sendiri.
Dukungan organisasi petani dan pemerintah daerah memungkinkan mereka mengolah tandan buah segar menjadi CPO tanpa sepenuhnya bergantung pada pabrik besar.
Imbasnya, nilai tambah lebih banyak tinggal di desa dan posisi tawar petani meningkat.
Contoh-contoh ini menegaskan bahwa kombinasi kebijakan tepat dan inisiatif lokal dapat menjadikan sektor perkebunan mesin pengentas kemiskinan.
https://money.kompas.com/read/2025/09/07/081500526/pertanian-motor-pengentasan-kemiskinan-dan-pengangguran
Terkini Lainnya