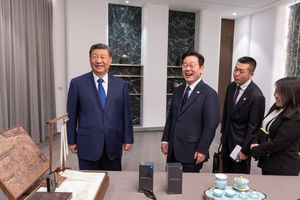Whoosh Bukan Investasi Sosial

Dalam pengukuran social return on investment (SROI), terdapat prinsip additionality, yakni dampak sosial baru yang tidak akan muncul tanpa proyek tersebut.
Dalam kasus Whoosh, manfaat semacam itu sulit dibuktikan. Justru terjadi peningkatan emisi selama konstruksi akibat penggunaan beton, baja, dan pembukaan lahan.
Kajian life-cycle assessment terhadap proyek kereta cepat di China yang dilakukan oleh Zhao dkk. dalam jurnal Transportation Research Part D: Transport and Environment (2022) menunjukkan bahwa manfaat pengurangan emisi baru terasa setelah sekitar empat dekade operasi, sedangkan beban sosial dan fiskal muncul sejak tahun pertama.
Secara empiris, efektivitas Whoosh pun belum terbukti. Sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023, jumlah penumpang hingga Februari 2025 baru mencapai sekitar delapan juta orang, dengan rata-rata harian 16.000–21.000 penumpang.
Angka ini jauh di bawah target studi kelayakan yang memproyeksikan 50.000–76.000 penumpang per hari.
Harga tiket yang berkisar Rp 150.000 hingga Rp 600.000 jelas belum terjangkau mayoritas masyarakat.
Dengan biaya proyek mencapai sekitar Rp 110 triliun, rasio biaya terhadap manfaat sosial tampak tidak seimbang dan memperlihatkan jurang antara narasi efisiensi dan realitas keterjangkauan publik.
Baca juga: Menakar Konsekuensi jika Gagal Bayar Utang Whoosh
Jika dari sudut inovasi sosial, Whoosh gagal menciptakan nilai baru, dari perspektif investasi sosial kesalahannya bahkan lebih mendasar.
Dari sisi investasi sosial, kesalahannya juga jelas. Dalam teori social investment yang dikembangkan oleh Nathalie Morel, Bruno Palier, dan Joakim Palme dalam Towards a Social Investment Welfare State? (2012), investasi sosial berbeda dari investasi fisik.
Ia fokus pada manusia, mencakup pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas produktif masyarakat.
OECD melalui laporan Social Expenditure Update (2020) menegaskan bahwa investasi sosial harus bersifat redistributif, berkelanjutan secara fiskal, dan memberi manfaat jangka panjang bagi kelompok rentan. Whoosh gagal dalam ketiganya.
Ia tidak memperluas akses kelompok miskin terhadap layanan dasar, tidak mengurangi ketimpangan wilayah, dan justru menambah beban fiskal melalui subsidi serta bunga utang jangka panjang yang diwariskan lintas generasi.
Jokowi berasumsi bahwa manfaat sosial eksternal seperti efisiensi waktu dapat membenarkan ketidakefisienan keuangan internal.
Padahal, dalam kerangka blended value creation, keberlanjutan sosial hanya tercapai jika keadilan dan efisiensi berjalan beriringan.
Ketika kerugian negara dibenarkan dengan alasan moral, pemerintah kehilangan insentif untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi fiskal.