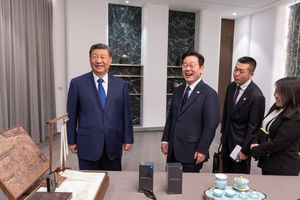Whoosh Bukan Investasi Sosial

DI TENGAH hangatnya perdebatan publik soal utang dan pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 Joko Widodo muncul dengan pembelaan yang menarik untuk bahas.
Ia menyebut proyek tersebut bukan beban keuangan negara, melainkan “investasi sosial” yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Klaimnya seperti sangat meyakinkan, tetapi benarkah logika tersebut?
Dari sudut pandang teori inovasi sosial seperti dikemukakan Geoff Mulgan (The Process of Social Innovation, 2007) dan Alex Nicholls serta Alex Murdock (Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets, 2012), klaim Presiden Jokowi bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial justru menunjukkan logika terbalik.
Inovasi sosial menilai sebuah inisiatif bukan dari besarnya skala proyek, tetapi dari sejauh mana ia mampu memperkuat partisipasi masyarakat dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.
Dalam kerangka itu, klaim Jokowi mengasumsikan bahwa nilai sosial dapat dihasilkan secara otomatis melalui pembangunan infrastruktur besar. Padahal inovasi sosial sejati menolak logika top-down semacam itu.
Baca juga: Whoosh dan Ujian Anti-Korupsi Prabowo
Alih-alih memperluas akses dan memberdayakan warga, Whoosh justru menegaskan ketimpangan dengan manfaat terbatas, minim partisipasi publik, dan bergantung pada utang serta subsidi.
Proyek Whoosh gagal memenuhi semua unsur itu. Dari sisi kebaruan, Whoosh bukan terobosan sosial, melainkan substitusi atau komplementer teknologi yang mempercepat perjalanan antarkota tanpa memperbaiki struktur mobilitas sosial.
Masalah kemacetan di Jakarta dan Bandung bukan karena lambatnya moda antar-kota, melainkan karena sistem transportasi di dalam kota yang timpang dan belum terintegrasi.
Inovasi sosial sejatinya menekankan perubahan yang menghubungkan transportasi, perumahan, dan lapangan kerja agar jarak sosial-ekonomi dapat dipersempit.
Whoosh tidak menyentuh akar masalah itu dan lebih menonjolkan simbol modernitas daripada pemerataan akses mobilitas.
Dari sisi partisipasi, proyek ini mencerminkan dominasi teknokratik (technocratic capture). Semua keputusan diambil secara tertutup oleh pemerintah pusat, BUMN, dan investor China tanpa melibatkan masyarakat sekitar atau pemerintah daerah.
Padahal, dalam konsep open innovation for social impact yang dijelaskan oleh Henry Chesbrough dalam Open Innovation Results (2020), nilai sosial hanya tercipta jika masyarakat ikut dalam proses perencanaan dan evaluasi.
Tanpa partisipasi publik, yang lahir bukan inovasi sosial, melainkan proyek elitis berbiaya tinggi dengan manfaat yang terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Klaim keuntungan sosial yang didasarkan pada efisiensi waktu dan penurunan emisi juga lemah secara metodologis.