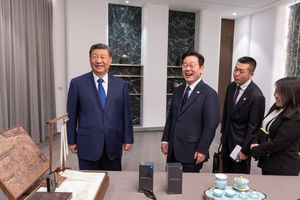Rojali, Rohana, Rohalus: Daya Beli Melemah atau Gaya Belanja Berubah?

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah menembus 229,4 juta orang, atau lebih dari 80 persen populasi.
Dari jumlah itu, sebagian besar menggunakan internet untuk aktivitas belanja daring, baik melalui aplikasi e-commerce, media sosial, maupun live shopping.
Data Bank Indonesia juga mengonfirmasi tren serupa. Berdasarkan data terbaru Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berhasil membukukan 6,05 miliar transaksi dengan total nilai mencapai Rp 579 triliun.
Transaksi melalui QRIS juga semakin dominan, melibatkan jutaan merchant kecil di seluruh pelosok Indonesia. Dengan kata lain, meskipun pusat perbelanjaan masih ramai, pusat aktivitas ekonomi kini bergeser ke layar gawai di tangan konsumen.
Pergeseran ini membawa implikasi bahwa konsumen lebih cenderung membandingkan harga secara digital sebelum membeli.
Mal tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk “menemukan barang baru”. Justru, ia berfungsi sebagai ruang pamer, tempat masyarakat melihat langsung produk, mencoba, lalu membeli secara online dengan harga lebih murah. Inilah yang sering disebut sebagai fenomena showrooming.
Tidak heran bila kita sering menemukan pengunjung mal yang tampak serius memotret kode produk, membandingkan di marketplace, dan akhirnya tidak melakukan transaksi di toko fisik.
Maka, rohalus bukan semata tanda kantong kering, melainkan strategi rasional konsumen di era digital.
Fenomena rojali, rohana, rohalus juga tidak bisa dilepaskan dari pergeseran nilai konsumsi generasi muda, terutama Gen Z dan Milenial.
Saat ini lebih dari 60 persen Gen Z Indonesia lebih memilih membelanjakan uangnya untuk pengalaman ketimbang barang. Pergi ke kafe estetik, konser musik, atau sekadar nongkrong di mal sering dianggap lebih bermakna ketimbang membeli produk fashion atau gawai baru.
Hal ini menjelaskan mengapa food and beverage (F&B) menjadi salah satu sektor yang justru tumbuh pesat di mal, meskipun toko pakaian atau barang mewah mengalami stagnasi.
Bagi anak muda, nongkrong di kafe sambil membeli minuman kekinian seharga Rp 30.000–50.000 lebih bernilai sosial dibanding membeli kemeja Rp 300.000. Mal menjadi ruang sosial, bukan lagi ruang transaksi belaka.
Selain itu, generasi muda juga jauh lebih sadar harga. Dengan akses mudah ke berbagai platform belanja online, mereka terbiasa menjadi smart consumer, yaitu menunggu promo, memanfaatkan voucher, hingga menggunakan paylater.
Baca juga: Rent-Seeking Behaviour: Ketika Negara Sibuk Memungut, Lupa Menumbuhkan
Akibatnya, mereka tidak mudah tergoda untuk langsung membeli barang di toko fisik, apalagi jika tahu bisa mendapat harga lebih murah secara daring.
Fenomena ini tentu membawa konsekuensi serius bagi pelaku ritel. Mal tetap ramai, tetapi omzet toko tidak selalu ikut naik.
Sebagian tenant fashion, elektronik, dan aksesori melaporkan stagnasi penjualan, meski arus pengunjung tinggi. Tidak sedikit pula yang akhirnya memilih mengurangi ukuran toko fisik, mengganti strategi ke omnichannel — gabungan antara kehadiran offline dan online.
Bagi UMKM, pergeseran ini menghadirkan dua wajah. Di satu sisi, mereka semakin sulit bersaing dengan harga toko daring yang sering didukung promo besar-besaran dari platform e-commerce.
Namun di sisi lain, digitalisasi justru membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar tanpa harus bergantung pada lokasi fisik.
Pemerintah telah mendorong program digitalisasi UMKM, dengan target 50 juta UMKM onboarding ke e-commerce pada 2025. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana UMKM tidak hanya hadir, tetapi juga mampu bersaing secara sehat di ekosistem online.
Belanja, bagi banyak orang, bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga hiburan dan aspirasi. Mal menjadi ruang publik modern yang memberi kesempatan untuk merasakan atmosfer kelas menengah, bahkan bagi mereka yang tidak melakukan transaksi.
Dengan berjalan-jalan di mal, mencoba barang, atau sekadar berfoto di depan etalase, konsumen mendapatkan kepuasan psikologis tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.
Fenomena ini diperkuat oleh budaya media sosial. Tidak sedikit orang yang datang ke mal lebih untuk konten ketimbang belanja. Selfie di depan toko mewah, mengunggah story dari kafe populer, atau sekadar menunjukkan suasana mal baru menjadi bagian dari gaya hidup digital.
Maka, rojali bisa dibaca sebagai strategi masyarakat kelas menengah bawah untuk tetap merasa bagian dari arus gaya hidup urban tanpa harus menguras dompet.
Pertanyaan besar yang kemudian muncul, apakah maraknya rojali, rohana, dan rohalus menandakan krisis konsumsi, atau sekadar adaptasi gaya belanja?
Jawabannya mungkin ada di tengah. Memang benar ada tekanan daya beli, terutama pada kelas menengah bawah yang terhimpit inflasi pangan dan cicilan. Namun di saat bersamaan, konsumsi masyarakat tidak lenyap, hanya bergeser kanal dan prioritas.
Baca juga: Simbol Agama dan Rompi Oranye