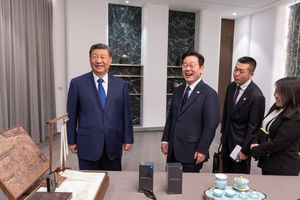Tragedi Kanjuruhan dan Krisis Penegakan HAM di Indonesia
Sebanyak 135 jiwa melayang dan ratusan lainnya terluka akibat peristiwa yang seharusnya tidak pernah terjadi.
Sepak bola, yang seharusnya menjadi ruang hiburan dan kegembiraan, justru berubah menjadi arena kematian.
Peristiwa ini menyingkap persoalan serius mengenai lemahnya pelindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan.
Kanjuruhan tidak bisa hanya dipandang sebagai “insiden sepak bola” semata; melainkan cermin dari rapuhnya sistem manajemen keamanan, budaya impunitas aparat, serta praktik bisnis yang mengabaikan aspek kemanusiaan.
Fakta penggunaan gas air mata di dalam stadion—meskipun jelas dilarang oleh regulasi FIFA—menjadi bukti nyata penggunaan kekuatan berlebih yang berujung pada pelanggaran hak paling fundamental: hak untuk hidup.
Pun, tragedi ini memperlihatkan krisis akuntabilitas negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.
Proses hukum berjalan lambat dan tidak menyentuh semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab, sementara korban dan keluarganya masih berjuang mendapatkan pemulihan yang layak.
Situasi ini mempertegas bahwa tragedi Kanjuruhan sejatinya bukan sekadar kecelakaan, melainkan refleksi dari krisis penegakan HAM di Indonesia yang masih jauh dari prinsip keadilan, kebenaran, dan penghormatan martabat manusia.
“Arah angin” sebagai dalih hukum
Alasan hakim yang menyatakan bahwa asap gas air mata hilang terbawa angin merupakan contoh nyata bagaimana hukum bisa kehilangan logika dan keadilan.
Dalam tragedi Kanjuruhan, lebih dari seratus nyawa melayang, ratusan orang luka-luka, dan puluhan anak menjadi korban.
Fakta yang tidak terbantahkan adalah aparat menembakkan gas air mata ke arah penonton, tindakan yang dilarang secara tegas oleh regulasi FIFA dan prinsip HAM internasional.
Gas air mata bukan sekadar asap biasa; melainkan senjata kimia yang efeknya terbukti menyebabkan sesak napas, iritasi parah, hingga asfiksia.
Menyalahkan “angin” sebagai faktor utama sama saja dengan melepaskan tanggung jawab manusia dan negara, lalu menggantinya dengan kambing hitam berupa fenomena alam.
Dalih ini jelas problematik karena menggeser perhatian publik dari inti persoalan: adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional.
Negara justru berlindung di balik argumentasi teknis yang dangkal, padahal prinsip dasar HAM menuntut akuntabilitas penuh. Pasal 28I UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup warganya.
Begitu pun ICCPR yang sudah diaksesi Indonesia, menyatakan hak hidup tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.
Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum malah menormalisasi penyalahgunaan kekuasaan. “Angin” dijadikan tameng untuk melanggengkan impunitas aparat, seolah-olah nyawa ratusan korban tidak pernah benar-benar ada.
Yang lebih menyakitkan, vonis ini menutup peluang bagi keluarga korban untuk memperoleh keadilan. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya pada sistem hukum jika kematian orang terdekatnya dijelaskan dengan retorika “angin”?
Putusan ini tidak hanya membebaskan aparat dari tanggung jawab, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Dalam HAM, keadilan substantif menuntut pengungkapan kebenaran, akuntabilitas pelaku, dan pemulihan korban. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: pengadilan menjadi ruang yang memutihkan kesalahan negara.
Ironinya, alasan “angin” pun mengabaikan bukti medis dan kesaksian korban. Banyak yang meninggal dengan gejala khas paparan gas air mata: wajah membiru, kesulitan bernapas, busa keluar dari mulut.
Fakta-fakta ini seolah tidak pernah dipertimbangkan. Padahal, secara ilmiah, efek gas air mata tidak serta-merta hilang hanya karena ada hembusan angin.
Justru di ruang tertutup dengan pintu sempit seperti stadion Kanjuruhan, gas itu akan memerangkap massa dalam kepanikan. Jika argumen hakim diikuti, maka setiap pelanggaran aparat bisa dengan mudah ditutupi dengan alasan “faktor alam” semata.
Instrumen HAM dan kewajiban negara
Tragedi Kanjuruhan harus dilihat melalui kacamata instrumen HAM, baik yang berlaku secara internasional maupun nasional.
Indonesia telah mengakui dan mengikatkan diri pada berbagai perjanjian internasional, termasuk ICCPR yang diaksesi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak inheren untuk hidup, dan hak ini tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.
Kewajiban negara tidak berhenti pada larangan membunuh warganya, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menindak setiap pelanggaran hak hidup.
Di level nasional, UUD NRI 1945 Pasal 28A dan 28I ayat (4) secara jelas menjamin hak hidup dan menegaskan kewajiban negara menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia.
Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pun menempatkan hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Maka, setiap praktik penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, terlebih yang berujung kematian massal, merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi dan undang-undang nasional yang berlaku.
Instrumen HAM pun menuntut akuntabilitas. United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990) menekankan bahwa aparat hanya boleh menggunakan kekuatan jika benar-benar diperlukan, dan harus dilakukan secara proporsional untuk melindungi nyawa.
Prinsip tersebut jelas diabaikan dalam kasus Kanjuruhan, gas air mata ditembakkan ke arah tribun penonton yang tidak menimbulkan ancaman langsung.
Pelanggaran ini menunjukkan ketidakpatuhan negara terhadap standar internasional yang seharusnya menjadi pedoman.
Dengan latar instrumen hukum tersebut, jelas bahwa tragedi Kanjuruhan bukan sekadar persoalan teknis keamanan stadion, tetapi pelanggaran serius terhadap kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.
Ketika negara gagal menegakkan instrumen hukum yang sudah disepakati, maka yang lahir adalah krisis kepercayaan, impunitas aparat, dan ketidakadilan bagi korban.
Tragedi ini menjadi bukti bahwa HAM di Indonesia masih sering berhenti di atas kertas, tanpa implementasi nyata dalam praktik.
Kewajiban negara dan akuntabilitas HAM
Dalam diskursus hukum hak asasi manusia, negara bukan hanya dituntut untuk tidak melakukan pelanggaran (negative obligations), tetapi juga diwajibkan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya (positive obligations).
Sejatinya, kewajiban negara atas HAM terbagi dalam tiga dimensi: to respect, to protect, and to fulfill. Artinya, negara tidak boleh melanggar HAM, harus mencegah pihak lain melanggar HAM, dan wajib mengambil langkah aktif untuk memastikan setiap warga negara menikmati hak-haknya.
Jika konsep ini diterapkan pada tragedi Kanjuruhan, jelas terlihat bahwa negara gagal dalam ketiga dimensi tersebut.
Pertama, kewajiban to respect dilanggar melalui tindakan aparat yang menembakkan gas air mata secara berlebihan dan tidak proporsional.
Kedua, kewajiban to protect diabaikan karena negara gagal mencegah praktik manajemen pertandingan yang buruk, misalnya dengan membiarkan penjualan tiket melebihi kapasitas stadion dan tidak memastikan jalur evakuasi aman.
Ketiga, kewajiban to fulfill juga tidak terpenuhi, terbukti dari absennya mekanisme pemulihan yang memadai bagi korban, baik dari sisi medis, psikologis, maupun kompensasi keadilan.
Selain itu, teori state accountability dalam HAM menegaskan bahwa negara tidak bisa melepaskan tanggung jawab hanya dengan menyalahkan aparat lapangan.
Menurut Clapham dalam Human Rights Obligations of Non-State Actors (2006), akuntabilitas negara meluas hingga ke seluruh rantai komando, termasuk pembuat kebijakan dan otoritas pengawas.
Dalam Tragedi Kanjuruhan, tanggung jawab bukan hanya milik aparat yang menembakkan gas air mata, melainkan juga penyelenggara liga, federasi sepak bola, hingga pejabat yang gagal mengantisipasi risiko.
Pendekatan ini diperkuat oleh doktrin due diligence yang dikembangkan Komisi HAM PBB, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah proaktif dalam mencegah pelanggaran HAM yang dapat diperkirakan sebelumnya.
Pertandingan Arema-Persebaya dikenal sebagai laga berisiko tinggi, tetapi negara tetap gagal menyiapkan pengamanan sesuai standar. Fakta ini menunjukkan kelalaian struktural, bukan sekadar kesalahan teknis.
Tragedi Kanjuruhan sejatinya bentuk pelanggaran HAM struktural. Negara lalai menjalankan kewajiban positifnya, aparat dibiarkan tanpa kontrol efektif, dan sistem hukum justru memberi ruang bagi impunitas.
Hal ini menguatkan pandangan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih berkutat pada retorika normatif, tanpa keberanian untuk menghadirkan akuntabilitas substantif.
Tragedi Kanjuruhan bukan hanya tragedi olahraga, melainkan tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan wajah buram penegakan HAM di Indonesia.
Negara gagal menjalankan kewajiban konstitusional dan internasionalnya, sementara aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ancaman.
Putusan pengadilan yang melemahkan akuntabilitas dengan dalih “angin” hanyalah simbol dari budaya impunitas yang terus dibiarkan hidup.
Selama negara masih menempatkan keamanan di atas hak asasi, selama hukum lebih sibuk mencari alasan daripada kebenaran, maka keadilan bagi korban akan selalu menjadi mimpi yang tertiup angin, dan krisis penegakan HAM di negeri ini hanya akan semakin dalam.
https://regional.kompas.com/read/2025/10/03/12491411/tragedi-kanjuruhan-dan-krisis-penegakan-ham-di-indonesia
Terkini Lainnya