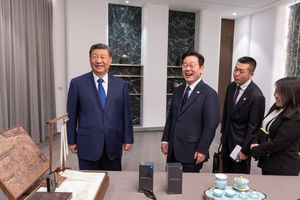Teater Jalanan di Sumut: Berebut Pajak Kendaraan Bermotor

DI TENGAH seretnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepala daerah tampaknya rela menjadikan jalan raya sebagai arena adu otot untuk mendongkrak kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Maka, jangan heran bila urusan pelat nomor berubah jadi adu gengsi antarprovinsi. Dan kejadian itu nyata di Pulau Sumatera.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution baru-baru ini menghentikan truk berpelat Aceh (BL) di jalan raya dan enteng meminta agar diganti pelat BK (plat kendaraan wilayah Sumut) seolah kendaraan Aceh melanggar hukum di tanah Sumut.
Gestur itu terekam video dan viral, lalu dibalas dari Banda Aceh dengan nada menantang, tapi tetap dibungkus kesantunan khas Aceh sekaligus.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak tinggal diam dan berujar, “Dipeu bloe, kamo bloe. Tapi tanyoe ta wanti-wanti chit. Menyoe ka di peubloe, ta bloe. Menyeu ka gatai ta garoe.”
Sederhananya, “kalau mau rebut, kami pun akan rebut. Tapi harus kita ingatkan dulu. Kalau sudah dijual, kita beli. Kalau gatal ya kita garuk.”
Kalimat itu tidak hanya menyulut emosi politik, ia juga mereduksi upaya pembungkaman administratif menjadi ala tontonan jalanan.
Baca juga: Penurunan TKD: Daerah Bisa Apa?
Secara hukum, posisi kendaraan berpelat BL sah untuk melintas di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjamin keabsahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari mana pun selama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) valid.
Indonesia tidak mengenal mekanisme paspor kendaraan antarprovinsi.
Plat nomor bukan izin melintas, tetapi jadi penanda registrasi fiskal di provinsi tempat kendaraan terdaftar.
Artinya, truk BL dapat saja dengan bebas keluar masuk Sumatera Utara, Jakarta, bahkan Papua, tanpa harus menanggalkan identitasnya. Logika ini fundamental dalam sistem hukum lalu lintas nasional.
Karena itu, ketika seorang gubernur menghentikan kendaraan dan meminta pelat diganti, publik wajar mempertanyakan dasar kewenangannya.
Kewenangan razia kendaraan juga tidak berada di tangan kepala daerah. Kewenangan itu melekat pada institusi kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas, dengan dukungan teknis Dinas Perhubungan dalam operasi gabungan.
Kepala daerah memang dapat mengeluarkan kebijakan fiskal atau regulasi daerah, tetapi tidak memiliki hak atributif untuk memberhentikan, memeriksa, apalagi menindak kendaraan di jalan raya.
Tindakan semacam itu, jika dilakukan, jatuh dalam kategori penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.
Oleh sebab itu, pembelaan bahwa aksi Bobby hanyalah sosialisasi sebenarnya merupakan pengakuan implisit bahwa ia sesungguhnya menyadari keterbatasan kewenangannya.
Namun, di mata publik, visualisasi gubernur menghentikan kendaraan di jalan raya sudah cukup kuat untuk memicu tafsir bahwa BL dianggap ilegal di Sumatera Utara.
Inilah yang membuat insiden ‘aksi ala koboi’ di jalanan itu lebih besar daripada sekadar salah paham.
Di balik itu terdapat logika fiskal yang ingin diperjuangkan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak provinsi. Penerimaannya masuk ke kas provinsi tempat kendaraan terdaftar.
Baca juga: Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas
Jika perusahaan logistik beroperasi penuh di Sumatera Utara tetapi mendaftarkan kendaraannya di Aceh, maka PKB dan BBNKB tentu akan mengalir ke Aceh.
Sumatera Utara hanya menanggung kerusakan jalan akibat truk-truk berat tersebut tanpa memperoleh penerimaan pajaknya. Dalam bahasa fiskal, kondisi ini adalah bentuk kebocoran antarwilayah.
Manfaat mengalir ke satu daerah, beban ditanggung daerah lain. Ibarat kata pemilik kendaraan plat B (Jakarta) yang tidak dimutasi dan berkeliaran di provinsi lain, bayar pajak di Jakarta tapi ‘merusak’ jalanan di mana-mana.
Tidak mengherankan jika Bobby mengangkat isu ini sebagai problem yang perlu diatasi.
Di sisi lain, Aceh dengan status otonomi khusus memiliki insentif untuk menarik sebanyak mungkin kendaraan berplat BL karena itu memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).