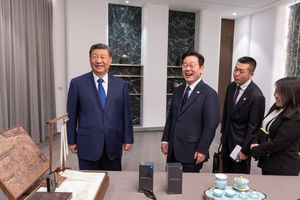"Rayap Besi": Metafora Ekologis dan Cermin Kerusakan Sosial
Ketika istilah “rayap besi” muncul di ruang publik—terutama melalui pemberitaan Kompas TV tentang penangkapan puluhan pelaku pencurian logam di Medan (Kompas.tv, 20/10/2025)—ia bukan sekadar permainan kata.
Istilah ini merupakan metafora ekologis yang merefleksikan bagaimana manusia memahami perilaku sosial melalui simbol-simbol alam.
Dalam hal ini, hewan yang dihadirkan bukan hanya untuk menggambarkan tindakan, tetapi juga untuk menilai moral di baliknya. Mirip penggunakan hewan dalam cerita fabel, ya?
Dalam fabel, hewan berbicara, berpikir, dan bertindak layaknya manusia. Namun, tujuan fabel bukanlah hiburan semata, melainkan pendidikan moral.
Rubah menggambarkan kelicikan, keledai melambangkan kebodohan, singa menyimbolkan kekuasaan.
Demikian pula dalam istilah "rayap besi", masyarakat menggunakan citra hewan untuk mengilustrasikan sifat sosial tertentu — kecil, tersembunyi, tapi bekerja bersama secara destruktif.
Ia adalah fabel baru dalam wacana perkotaan, yaitu kisah moral tentang bagaimana sekelompok makhluk kecil menggerogoti rumah yang tidak dijaga.
Berbeda dengan metafora populer seperti ular besi untuk kereta api, kuda besi untuk sepeda motor, atau burung besi untuk pesawat, istilah rayap besi memiliki nada moral yang jauh lebih gelap.
Ular besi melambangkan kecepatan dan kekuatan yang terarah, kuda besi menggambarkan semangat kebebasan dan mobilitas, sementara burung besi menyimbolkan kemajuan teknologi dan impian manusia menembus langit.
Ketiganya menggunakan kata “besi” untuk menegaskan kekuatan dan modernitas, tetapi tetap berasosiasi positif terhadap kemajuan.
Sebaliknya, rayap besi menandai kebalikan dari kemajuan itu. Secara ekologis, rayap memang tidak berbahaya karena ganas, melainkan karena diam-diam dan terorganisasi.
Itulah sebabnya metafora ini begitu kuat. Ketika kata rayap dipadankan dengan besi, muncul paradoks, yakni sesuatu yang kuat dan keras ternyata bisa digerogoti oleh sesuatu yang kecil dan tak terlihat, lho!
Secara semiotik, kata rayap mengandung asosiasi kecil, tersembunyi, sulit diberantas, dan merusak dari dalam.
Dalam konteks sosial, metafora ini menggambarkan perilaku destruktif yang dilakukan secara kolektif, tapi tidak kasatmata—seperti praktik pencurian, korupsi kecil, atau penyalahgunaan fasilitas publik yang lama-lama menggerogoti fondasi kota.
Berita tentang “puluhan rayap besi” yang ditangkap menambah bobot makna ini. Penanda “puluhan” memberi kesan ancaman yang masif dan sistemik: bukan satu dua individu nakal, tetapi gejala sosial yang merebak seperti koloni rayap.
Mereka bekerja dalam senyap, tidak terlihat di permukaan, tetapi meninggalkan kehancuran yang nyata.
Dengan metafora ini, para pelaku bukan hanya dikategorikan sebagai kriminal, melainkan simbol penyakit sosial yang merusak dari dalam—bagian dari ekosistem moral yang rapuh, bukan?
Menariknya, rayap dalam ekologi muncul karena ada yang tidak dijaga. Ia hidup di celah, di ruang yang lembap dan dibiarkan.
Artinya, dalam kerangka sosial, rayap besi tidak muncul begitu saja; mereka hadir karena kelalaian struktural—pengawasan yang lemah, kesenjangan ekonomi, atau sistem yang membiarkan peluang penyimpangan kecil tumbuh tanpa penanganan serius.
Kasus pencurian besi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Cakung, Jakarta Timur (tvOnenews.com, 9/6/25), rayap besi yang menggasak 1 unit mesin AC Outdoor di Aceh (aceh.viral, 7/6/25), maupun pencurian besi pembatas salah satu jembatan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa rayap besi bukan hanya “musuh” dari luar, tetapi juga cerminan dari kekosongan tanggung jawab.
Istilah ini menjadi kuat karena disebarkan oleh media, bukan hanya oleh masyarakat. Ketika media mengadopsi metafora ekologis seperti ini, ia memperkuat bingkai moral tertentu bahwa kejahatan harus dipahami layaknya wabah alam—datang diam-diam, menjalar perlahan, tapi mematikan bila tak segera diberantas.
Bahasa media, dalam hal ini, menjadi alat moral sekaligus politik. Ia tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga mengarahkan emosi dan opini publik terhadap pelaku kejahatan serta lembaga yang menanganinya.
Melalui rayap besi, media seolah membangun citra diri kota sebagai rumah, aparat dan masyarakat sebagai penjaga, serta kriminal sebagai hama.
Narasi ini memberi legitimasi moral bagi tindakan penegakan hukum dan sekaligus menegaskan batas antara “kami” yang menjaga dan “mereka” yang merusak.
Namun di balik kekuatan metafora ini, tersimpan peringatan bahwa rayap hanya berkembang di rumah yang dibiarkan rapuh. Artinya, masalah sosial yang berulang bukan hanya tentang pelaku, tetapi juga tentang sistem yang tidak belajar.
Dengan demikian, istilah rayap besi tidak sekadar memperkaya kosakata, melainkan membuka refleksi mendalam tentang hubungan antara bahasa, lingkungan, dan moralitas sosial.
Ia menegaskan bahwa dalam kebudayaan kita, hewan bukan sekadar bagian dari ekosistem alam, melainkan cermin perilaku manusia itu sendiri.
Di satu sisi, metafora ini efektif untuk menggugah kesadaran publik. Namun di sisi lain, ia menantang pemerintah dan masyarakat untuk tidak sekadar “membasmi rayap”, melainkan memperbaiki struktur rumah tempat rayap itu muncul.
Karena sejatinya, dalam rumah yang kuat dan terjaga, rayap takkan punya tempat untuk tumbuh, bukan?
https://regional.kompas.com/read/2025/10/29/12001741/rayap-besi-metafora-ekologis-dan-cermin-kerusakan-sosial
Terkini Lainnya