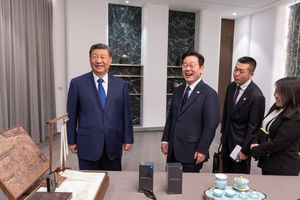Perampasan Tanah Adat Sihaporas dan Kolonialisme Gaya Baru

Lebih dari itu, lahan bagi masyarakat adat bukan hanya sekadar faktor produksi. Lahan adalah sumber identitas, tempat ritual, penanda sejarah, dan ruang spiritual yang diwariskan dari leluhur.
Hilangnya tanah berarti hilangnya seluruh makna hidup kolektif yang tidak bisa diganti dengan uang atau kompensasi material.
Namun, dalam kacamata pemilik modal, tanah hanya dilihat sebagai aset ekonomi. Paradigma inilah yang dikritik keras oleh Stefano Liberti dalam bukunya Land Grabbing: Journeys in the New Colonialism (2013).
Liberti menyingkap bagaimana tanah di abad ke-21 telah berubah menjadi komoditas global yang diperdagangkan dan diperebutkan, tak ubahnya saham atau obligasi.
Perusahaan multinasional, maupun investor lokal, negara kaya, hingga investor finansial, memburu lahan di selatan dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan, bioenergi, atau sekadar spekulasi investasi.
Persis seperti yang terjadi di Toba, tanah adat diubah menjadi ruang produksi bagi industri pulp yang pasarnya global.
Kepentingan lokal dipinggirkan, sementara logika kapital menguasai narasi pembangunan.
Dalam kasus Sihaporas, kita melihat bagaimana absennya Social License to Operate (SLO). Perusahaan boleh saja memiliki izin formal dari negara, tetapi tanpa penerimaan sosial dari komunitas lokal, operasionalnya tidak akan pernah mendapatkan legitimasi moral dan sosial.
TPL memang memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), tetapi masyarakat adat jelas menolak.
Ketika penolakan itu dibalas dengan kekerasan, terbukti bahwa perusahaan beroperasi tanpa lisensi sosial. Inilah yang memperlihatkan lemahnya moral ekonomi pemodal.
Mereka mengabaikan fakta bahwa bisnis yang mengorbankan hak asasi masyarakat lokal tidak pernah bisa disebut berkelanjutan.
Lebih buruk lagi, aparat negara sering terlihat berdiri di sisi pemodal. Keterlambatan polisi datang ke lokasi bentrokan hanya memperkuat kesan bahwa negara tidak netral. Alih-alih melindungi rakyat, aparat kerap berperan sebagai tameng perusahaan.
Inilah wujud moral hazard dari negara yang lebih memilih stabilitas bisnis ketimbang keadilan sosial. Negara seakan lupa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.
Namun, pengakuan tersebut nyatanya tidak otomatis diterjemahkan menjadi perlindungan nyata di lapangan. Sebaliknya, masyarakat adat masih terus dianggap sebagai penghalang pembangunan.
Dalam perspektif Liberti, kondisi ini mencerminkan suatu bentuk kolonialisme baru. Jika dulu tanah dirampas dengan bedil dan administrasi kolonial, kini tanah direbut melalui izin konsesi, dalih investasi, dan sokongan aparat. Bedanya hanya pada instrumen, bukan pada substansi.