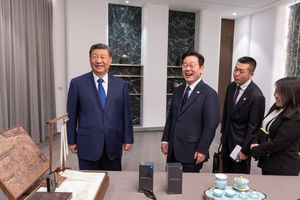Perampasan Tanah Adat Sihaporas dan Kolonialisme Gaya Baru

Kolonialisme lama menaklukkan bangsa lain, kolonialisme baru menaklukkan komunitas sendiri demi akumulasi modal global.
Bagi masyarakat adat, perbedaan tersebut tidaklah berarti apa-apa, mereka tetap kehilangan tanah, sumber penghidupan, dan identitas yang sesungguhnya merupakan warisan turun temurun.
Kerapuhan moral ekonomi pemodal terlihat jelas ketika keuntungan diprioritaskan di atas martabat manusia.
Perusahaan pulp mungkin membanggakan kontribusi terhadap devisa atau penciptaan kerja, tetapi angka-angka itu tidak pernah sebanding dengan kerugian sosial yang diderita warga.
Begitu pula aparat negara yang seharusnya menjadi penyeimbang, malah menjadi pelindung kepentingan kapital.
Ketika negara memilih berdiri di sisi modal, masyarakat adat ditinggalkan tanpa perlindungan hukum. Pada titik inilah kita melihat persekongkolan antara pemodal dan negara sebagai bentuk kegagalan moral bersama dari keduanya.
Hak masyarakat adat atas tanah harus dipandang lebih dari sekadar isu ekonomi. Hak masyarakat adat adalah hak kultural dan spiritual yang dijamin oleh konstitusi, pun oleh instrumen HAM internasional.
Kehilangan tanah adat berarti kehilangan naskah sejarah, hilangnya situs ritual, dan terhapusnya pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun.
Nilai-nilai ini tidak bisa diganti oleh skema kompensasi, seberapa pun besarnya. Ironisnya, dalam wacana pembangunan nasional, dimensi kultural dan spiritual ini sering dikesampingkan, dianggap tidak relevan dengan logika ekonomi modern.
Padahal, justru di situlah inti dari keberlanjutan, yakni pembangunan yang tidak memutus akar budaya masyarakat.
Konflik Sihaporas menjadi peringatan keras bahwa pembangunan yang dipaksakan tanpa penghormatan pada masyarakat adat akan selalu melahirkan resistensi.
Janji kesejahteraan tidak akan berarti jika janji tersebut dibangun di atas penderitaan komunitas yang telah bermukim di sana sejak dulu kala.
Social License to Operate hanya bisa hadir ketika ada partisipasi setara, penghormatan pada hak adat, dan mekanisme distribusi manfaat yang adil.
Tanpa itu, perusahaan hanya beroperasi dengan legalitas formal, tetapi kehilangan legitimasi moral. Dan pada akhirnya, perusahaan seperti ini hanya menambah panjang daftar aktor dalam perampasan tanah global yang dikritik Liberti sebagai wajah baru kolonialisme.
Melihat pola berulang ini, sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata. Negara seharusnya hadir menjadi pelindung masyarakat adat, bukan fasilitator modal.
Negara harus mengakui bahwa perampasan tanah adat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Bukan sekadar sengketa agraria biasa, melainkan kejahatan yang merampas identitas, budaya, dan kehidupan spiritual sebuah komunitas.
Jika negara terus membiarkan, maka kita sedang menyaksikan kolonialisme baru yang lahir di tanah air sendiri. Jika kasus kekerasan terhadap rakyat ini terus berlanjut, maka manusia di Indonesia sesungguhnya belum benar-benar merdeka.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang